Say No to Racism!
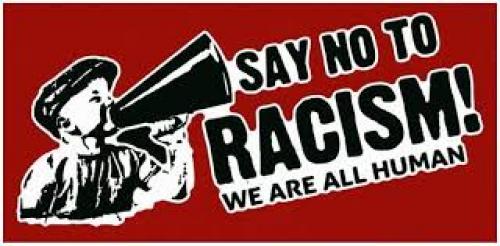
Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Sistem demokrasi itu membantu Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang sebagai sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur. Peranan sistem demokrasi itu tampak nyata di dalam keseharian hidup masyarakat Indonesia sejak era kemerdekaan sampai pada detik ini.
Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, perbedaan pendapat itu lumrah. Sebab, setiap orang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi tentang segala sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat dengan segala macam kompleksitasnya. Maka, perbenturan ide atau gagasan tidak dapat dihindari, bahkan menjadi sajian yang perlu dan penting untuk mewarnai kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dan negara.
John Rawls, sebagaimana dikutip Yosef Keladu dalam artikel berjudul “Konsep Hannah Arendt tentang Politik sebagai Pembicaraan dan Kontribusinya dalam Menyikapi Pluralitas Pandangan” (2005), menyebut kondisi ini sebagai pluralisme masuk akal (reasonable pluralism) yang muncul karena setiap pandangan dirumuskan oleh orang-orang yang berakal budi sehat dan “mulai dari dalam pandangan komprehensif mereka sendiri dan bertolak dari dasar religius, filosofis, dan moral mereka sendiri”.
Sementara itu, Chantal Mouffe (1998) menyebut pluralisme masuk akal itu dengan pluralisme agonistis karena dalam politik selalu ada perjuangan, konflik atau persaingan tentang isu-isu atau masalah-masalah bersama. Dengan kata lain, politik selalu berkarakter demokratis karena terdiri atas domesticating enmity dengan mengizinkan pandangan-pandangan yang bersaing untuk ada dalam relasi manusia (Daven, M. dan Kirchberger, G. (ed.), 2019: 64).
Maka, perbedaan pendapat itu mesti dihargai dan dihormati eksistensinya di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dapat ditunjukkan lewat sikap-sikap yang baik, beradab dan bermartabat, bukan sikap-sikap yang buruk seperti marah, dendam, maupun perilaku dan tindakan rasis. Sebab, perbedaan pendapat merupakan rahmat dan anugerah untuk mempertajam pertimbangan-pertimbangan, diskursus, dan musyawarah ketika melakukan pertemuan atau sidang tertentu.
Pada titik ini, perbedaan pendapat tidak bisa menjadi alasan atau basis legitimasi dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan destruktif terhadap sesama, termasuk tindakan rasis. Sebab, dalam beberapa hari terakhir, ruang publik Indonesia dihebohkan oleh sikap, perilaku, dan tindakan rasis dari Ambroncius Nababan dan Permadi Arya terhadap Natalius Pigai yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat di antara mereka. Penulis menegaskan bahwa perbedaan pendapat antara Natalius, Permadi, dan Ambroncius tidak dapat melegitimasi Permadi dan Ambroncius untuk melakukan tindakan rasis terhadap Natalius.
Rasisme, sebagaimana yang terjadi pada Natalius Pigai, merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Rasisme menciptakan keresahan tersendiri di tengah masyarakat, khususnya keresahan yang terjadi pada korban rasis. Sebab, rasisme itu telah melecehkan dan merendahkan martabat manusia dari para korban rasis.
David Newman (2012: 405), mendefinisikan rasisme sebagai believe that human are subdivided into distict group that are different in their social behavior and innate capacities and that can be ranked as superior or inferior in the matter of race. Di sini, Newman melihat rasisme sebagai pembagian manusia ke dalam kelompok yang berbeda-beda berdasarkan perilaku sosial dan kapasitas bawaannya, sehingga terbentuk kelompok yang lebih superior dan inferior dalam soal ras. Misalnya, dari sisi kapasitas bawaan, rasisme itu berkaitan erat dengan ciri-ciri fisik manusia seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, bentuk mata dan kondisi fisik lainnya.
Biasanya, orang yang berkulit hitam dan berambut keriting dinilai lebih inferior daripada orang yang berkulit putih dan berambut lurus. Hal itu pernah terjadi di Afrika Selatan dalam politik Apartheid. Orang Eropa yang berkulit putih dan berambut lurus dianggap lebih unggul dalam segala hal daripada penduduk asli Afrika Selatan yang berkulit hitam dan berambut keriting. Akibatnya, sikap, perilaku dan tindakan diskriminatif terjadi di pelbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial-politik, ekonomi, hukum, budaya, seni, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
Komitmen Bersama untuk Menolak Rasisme
Bernard Raho (2016: 195) mengatakan bahwa kenyataan-kenyataan biologis seperti bentuk tubuh atau warna kulit sama sekali tidak ada hubungan dengan kualitas-kualitas kemanusiaan, seperti kemampuan intelektual atau kematangan emosional. Kekeliruan yang mencampuradukkan bentuk fisik dengan kualitas kemanusiaan telah memunculkan kategori-kategori yang bersifat rasial, walaupun dalam kenyataannya kategori-kategori itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kategori-kategori yang bersifat rasial itu tidak memiliki basis argumentasi yang kokoh untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, rasisme mesti ditolak.
Penolakan kita terhadap rasisme mesti dibuktikan dalam tindakan konkret. Salah satu caranya ialah dengan membangun komitmen bersama untuk selalu mengatakan “Say no to racism!” di dalam kehidupan kita sehari-hari. Komitmen bersama semacam ini berperan penting untuk menjaga dan melindungi diri kita dari sikap, perilaku dan tindakan rasisme terhadap sesama di sekitar kita.
Untuk memperkuat dan meneguhkan komitmen bersama dalam menolak rasisme itu, kita perlu belajar dari sepak bola. Sebab, menurut Handoko dalam Mas Yongky Satria, dkk. (2020: 4-5), dengan artikel berjudul “Bonek Tionghoa: Menolak Rasisme melalui Komunikasi Simbolik”, sepak bola menjadi cabang olahraga yang paling multikultural di antara cabang olahraga yang lain. Sepak bola menjadi salah satu olahraga yang berhasil mendobrak sekat sosial, kultural, etnis, agama, ideologi, dan negara. Sportivitas sepak bola dimaknai dengan sikap inklusif oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan sepak bola seperti pemain, pelatih, suporter, wasit, dan lain-lain.
Dalam hal ini, sepak bola adalah medan belajar untuk menghilangkan etnosentrisme, fanatisme dan eksklusivisme sempit. Makanya, sepak bola di seluruh dunia selalu kompak untuk menolak diskriminasi seperti rasisme dengan menjunjung tinggi prinsip “No to Racism!” di setiap event atau pertandingan sepak bola.
Dari sisi pemerintah dan pihak berwajib, komitmen bersama untuk menolak rasisme dapat ditunjukkan dalam usaha penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan tindakan rasisme. Pemerintah dan pihak berwajib mesti menyikapi persoalan ini secara tegas dengan berpihak pada korban tindakan rasisme, serta memberikan hukuman yang setimpal sesuai hukum positif kepada para pelaku tindakan rasisme. Sebab, pada dasarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Armiwulan, H., 2015). Oleh karena itu, pemerintah dan pihak berwajib mesti melaksanakan amanat konstitusi itu dengan menyelesaikan segala persoalan yang bersifat diskriminatif dengan adil, khususnya rasisme.
Akhirnya, penulis berharap agar tindakan rasisme dan semua jenis diskriminasi yang lain dapat segera “lenyap” dari tanah Nusantara untuk menciptakan kehidupan yang lebih beradab dan bermartabat sebagai insan-insan bumi pertiwi.
Artikel Lainnya
-
202503/11/2019
-
180205/07/2020
-
14001/01/2025
-
Kylian Mbappe, Bintang Baru dari Perancis
62118/12/2022 -
Strategi Penerapan Komunikasi Lingkungan Terhadap Krisis Air di Indonesia
9926/01/2025 -
Kuasa Pemodal dan Jeritan Masyarakat
174208/09/2020
