Sastra 'Keran Air Patah'
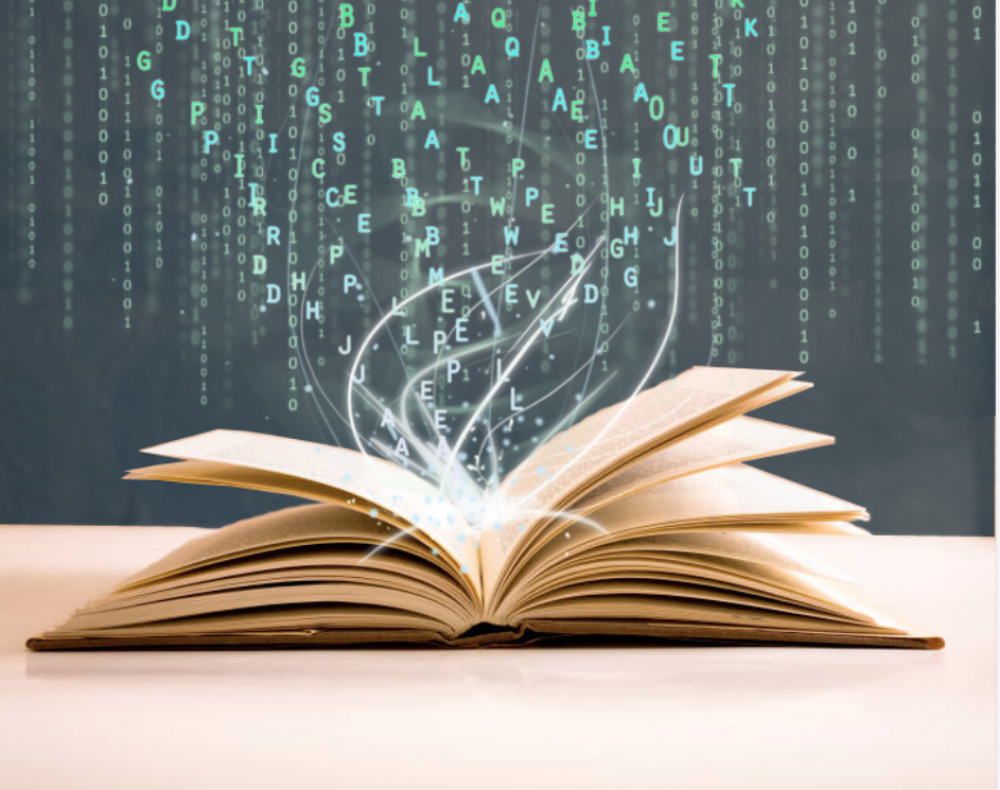
Bagai keran air yang sudah patah dan yang airnya menyembur ke segala arah tanpa terbendung lagi, demikian pula nasib sastra cyber era ini. Bentuk-bentuk ekspresi sastra digital membasahi berbagai media dan platform sosial tanpa filtrasi. Ini adalah sebuah bentuk demokratisasi baru dalam dunia kesusastraan.
Istilah sastra cyber sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Ia mencapai puncak popularitasnya bersamaan dengan klimaks kejayaan teknologi informasi sejak awal 2000-an. Dalam ruang sastra cyber, teknologi informasi dan internet menjadi rahim yang melahirkan sastrawan-sastrawan baru.
Dalam sastra cyber, untuk menjelma sebagai seorang sastrawan, seseorang tidak lagi dibatasi oleh birokrasi meja redaksi yang super ketat. Status sebagai sastrawan tak lagi menjadi privilese bagi sebagian kecil golongan saja, melainkan kini menjadi gelar bagi siapa saja yang berhasil menerbitkan karyanya di media sosial. Tak peduli jika ia baru menerbitkan satu karangan sekali pun.
Sistem redaksi media yang bertindak bagaikan keran yang membatasi volume gagasan dan debit kelayakan sebuah tulisan tak lagi berfungsi dengan baik karena sudah dipatahkan. Karangan-karangan sastra mengalir keluar tak ada batasan lagi. Setiap orang mampu dan berhak menghasilkan sebuah karya cipta di jagad maya.
Tak tanggung-tanggung, beberapa aplikasi memfasilitasi gairah para penulis yang ingin karyanya secara instan dipublikasikan. Beberapa diantaranya seperti FunFiction, Wattpad, Facebook, dan Twitlonger. Dengan berbekal kemauan, meskipun tanpa diimbangi dengan kemampuan yang memadai, para penulis ini memanfaatkan platform tersebut untuk mengorbitkan karyanya tanpa melalui mata redaksi.
Meskipun demikian, masih cukup banyak media dan website online yang memberlakukan sistem redaksi dan seleksi yang ketat. Siapa pun yang ingin mengirimkan karyanya harus menerima konsekuensi ini. Namun, kalau pun tidak diterima, seseorang masih tetap bisa membagikan karya sastranya secara gratis kepada publik melalui ratusan opsi platform media lain. Tak banyak penulis yang menempuh jalan ini.
Tema-tema karya sastra cyber hadir dengan kemasan yang semakin beragam. Persoalan yang paling sepele dan lazim sekali pun bisa dikemas menjadi karya sastra. Trend-trend dunia milenial dibalut sedemikian rupa menjadi sajian sastra yang sangat remeh temeh tapi tetap artistik. Ide-idenya tak lagi terlalu filosofis, nasionalis, metafisis, akademis, atau politis. Banyak yang menulis secara spontan, emosional, jujur, partikular, remah-remah, dan sederhana.
Kita turut berbangga dengan perkembangan yang ada. Dengan tidak mengurangi rasa bangga kita terhadap kemudahan sastra cyber, kita masih perlu memetakan posisinya dalam kerangka yang lebih komprehensif. Apakah sastra cyber adalah cerminan yang ideal dari sastra? Seberapa berkualitas tulisan-tulisan sastra yang bertebaran di media-media sosial? Dengan ketiadaan beban dan batasan redaksi, apakah semua tulisan layak disebut sebagai sebuah karya sastra? Apa saja batu sandungan yang perlu dibuang dalam sistim sastra digital?
Sastra Anarkis
Karya-karya sastra cyber bersifat anarkis. Internet memampukan tulisan-tulisan tersebut terbit dan kebal terhadap segala regulasi dan standar-standar kelayakan sebuah karya. Bisa dibayangkan, apa jadinya citra sastra bila tidak ada lagi kurasi dan proses seleksi yang jelas. Padahal sebuah tulisan belum tentu dianggap sebagai karya sastra. Meskipun secara subjektif orang bisa menilai tulisan apa saja sebagai sebuah karya sastra, secara objektif ada standar-standar yang harus dipenuhi agar layak disebut sebagai karya sastra.
Kemampuan berbahasa, entah lisan atau tulisan, adalah medium utama dalam karya sastra. Kecakapan dalam aktivitas berbahasa didaulat sebagai patokan objektif dasar dalam karya sastra. Jika tuntutan objektif ini tidak dipenuhi, atau dipenuhi secara parsial saja, tulisan tersebut belum bisa dianggap sebagai sebuah karya sastra.
Minimnya sistim kontrol meja redaksi membuka peluang besar kepada tindakan plagiarisme. Karena tidak ada ‘polisi’ yang mengawasi geliat sastra, ia bisa saja berkembang menjadi sastra perampok yang menjadikan ide orang lain sebagai properti tulisan pribadinya.
Ketiadaan sistim kurasi juga berdampak buruk terhadap outcome tulisan sastra di internet. Karya sastra yang dihasilkan tidak lagi memperhatikan kaidah berbahasa dan aturan kepenulisan. Kalimat, ejaan dan diksi yang buruk semakin mencoreng kualitas sastra digital. Para penulis pemula melanggar standar-standar kepenulisan. Padahal kemampuan berbahasa yang baik menjadi modal utama seorang sastrawan sejati.
Hal ini sangat beralasan dan dapat dipahami, karena pada umumnya sastra cyber adalah tulisan yang tidak diterima di media cetak. Pasca ditolak dengan alasan kurasi, dengan bantuan internet, penulis bersangkutan masih bisa membagikan karyanya kepada publik. Karya dengan kualitas minimalis itu akhirnya masih bisa berkeliaran di jagad maya
Banyak terjadi perdebatan tentang karya-karya sastra cyber. Ada yang menganggap karya-karya itu sebenarnya kurang berkualitas dibandingkan tulisan-tulisan sastra di media cetak. Beberapa buku antologi kumpulan karya sastra cyber yang diterbitkan sempat memantik ketidaksetujuan.
Pada tanggal 9 Mei 2001 diterbitkan sebuah buku antologi puisi cyber berjudul Graffiti Gratitude oleh Sutan Ikwan Soekri Munaf. Cerpen cyber dengan judul Graffiti Imaji diterbitkan tahun 2002, diikuti buku antologi esai Cyber Graffiti: Polemik Sastra Cyberpunk pada 2004. Karya-karya ini menjadi pionir pertama yang membukukan karya-karya sastra cyber kepada para penikmat sastra.
Menurut Hilda Septriani banyak orang yang terjun dalam sastra cyber karena menganggap sistim cetak dan buku terlalu hegemonik. Ada kekuasaan yang membatasi kebebasan para penulis. Banyak yang ingin lari dari kerumitan proses kurasi sebuah tulisan. Belum lagi jika setiap media atau lembaga penerbitan cetak punya ideologi politik atau orientasi bisnis tertentu.
Mari Berbenah
Sebagai usaha untuk terus merangkum semakin banyak sastrawan baru dan untuk tetap menyajikan karya sastra yang berkualitas, kiranya tiga catatan penting ini perlu dilirik barangkali sejenak. Semoga bisa jadi bahan untuk berbenah.
Pertama, sastra cyber juga punya hak untuk eksis dan bertumbuh di dunia wacana masyarakat. Terlepas dari tudingan miring atasnya yang mengidentikkan sastra ini sebagai ‘sampah’ atau ‘anak haram’, ia juga punya aspek yang menjanjikan.
Karya sastra cyber adalah cerminan yang paling dekat dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Kelahiran dan perkembangannya berawal dari trend masyarakat umum dengan segala isu, karakter dan kemurniannya. Dari sana kita bisa melihat gagasan dan keprihatinan masyarakat yang sering tertuang dalam tulisan berbalut sastra. Sastra cyber adalah sastra rakyat alih-alih sastra aristokrat. Membaca karya sastra cyber sama halnya membaca wajah masyarakat.
Kedua, jika karya cyber tidak melewati mekanisme kurasi tulisan, setidaknya para penulis tergerak untuk menjadi redaktur bagi tulisannya sendiri. Setiap penulis punya tanggungjawab moral terhadap apa yang ia tuliskan. Maka sejak perencanaan dan penggarapan, ia harus meredaksi produk tulisannya baik secara teknis kebahasaan, maupun secara non-teknis dan gagasan.
Untuk mewujudkan visi ini, seorang penulis harus memiliki seperangkat kemampuan dasar. Mereka harus paham kaidah kebahasaan, perihal originalitas, logika menulis, dan tujuan tulisan mereka. Keempat elemen ini harus terintegrasi dalam karya agar memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Ketiga, dalam semesta wacana, publik pembaca bisa menjadi redaktur yang membangun. Selain kurasi oleh penulis sendiri, komentar, kritik dan masukan dari para penikmat karya sastra cyber bisa menjadi pelajaran penting untuk menciptakan karya yang lebih baik. Penilaian oleh publik memampukan kita mengetahui batas kemampuan dan kualitas karya yang kita buat.
Karya-karya sastra cyber berjubelan di ruang-ruang maya. Dengan semaraknya karya-karya itu, berlakulah hukum evolusi ala Darwin, the finest for the fittest. Karya yang unggul dan berkualitas akan lebih banyak mendapat perhatian dan bertahan. Untuk itu, jika setiap penulis ingin bertahan, ia harus mulai mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dan yang paling penting ‘berevolusi’ dengan lanskap karakter pembaca dan konteks yang sedang berlangsung, serta rendah hati menerima kritik dan saran. Mari berbenah.
Artikel Lainnya
-
162402/08/2020
-
15002/08/2025
-
22623/07/2024
-
Jokowi dan Kemunduran Demokrasi Indonesia
224030/01/2020 -
Ancaman Money Politic dan Golput di Pilkada
164220/11/2020 -
Perempuan dan Polemik Pernikahan Dini
104117/03/2022
