Memasyarakatkan Warga Binaan Pemasyarakatan
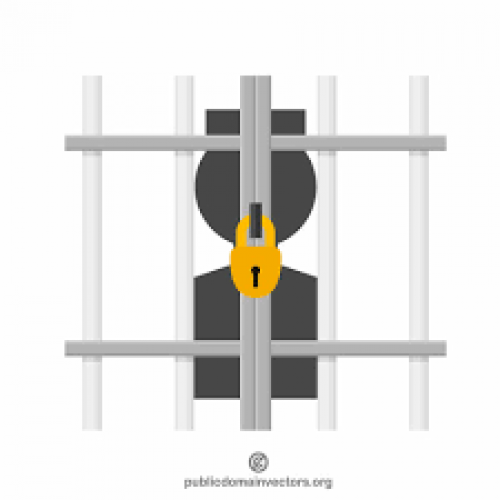
Kata pemasyarakatan, untuk sebagian besar masyarakat awam sangat asing ditelinga. Berbeda dengan kata penjara di mana kata tersebut sudah sangat familiar di masyarakat. Sampai sekarang di dalam mindset masyarakat kita, mantan warga binaan pemasyarakatan atau lebih sering disebut narapidana masih dipandang sebelah mata, bahkan yang menyedihkan banyak juga yang tutup mata. Persepsi yang ada di mayoritas masyarakat bahwa mantan narapidana adalah orang jahat yang harus dijauhi, dihindari, dan dikucilkan.
Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Ini adalah konsekuensi logis akan tindakan mereka di masa lampau, di mana mereka sudah melakukan pelanggaran hukum dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
Setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap suatu hal, baik itu yang ada dalam diri sendiri atau orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Erving Goffman dalam teorinya mengenai diri (self), yaitu bagaimana seseorang memaknai dirinya sendiri sebelum mendengar tentang dirinya dari orang lain. Goffman mendefinisikan stigma sebagai situasi individu yang terdiskualifikasi dari penerimaan sosial yang utuh atau situasi yang tidak menerima penerimaan utuh.
Inilah yang menjadi masalah besar di masyarakat kita ketika akan memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan. Sejak dulu stigma mayoritas masyarakat sudah terbentuk di mana lembaga pemasyarakatan atau lazim disebut penjara itu adalah tempat orang jahat dihukum, disiksa, dirampas kemerdekaannya, dan tempat segala macam kesusahan dengan tujuan membuat jera.
Maka, seseorang yang sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan banyak tidak diterima kembali di masyarakat karena dianggap sudah tidak bermoral. Seperti yang dikemukakan oleh Erving Goffman yang menggunakan konsep stigma untuk menggambarkan suatu proses yang mana orang-orang tertentu secara moral dianggap tidak berharga atau dengan kata lain stigma merupakan sikap, perlakuan, atau perilaku masyarakat yang memandang perilaku tertentu sebagai hal yang buruk sebagai orang yang secara moral tidak berharga.
Salah satu bukti konkret dari diskriminasi yang dialami oleh mantan narapidana adalah ketika mantan narapidana sudah kembali ke dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan karena banyak perusahaan atau pemilik usaha enggan memperkerjakan mereka sebagai pegawai.
Seorang mantan narapidana merupakan kelompok yang rentan dalam masyarakat. Sebagai kelompok rentan terhadap ancaman, mantan narapidana seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi termasuk dalam mendapatkan pekerjaan. Karena kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, ditambah lagi dengan desakan kebutuhan ekonomi, terkadang membuat seorang mantan narapidana melakukan kembali kejahatan (residivis).
Padalahal konsep baru sudah dikenalkan oleh Saharjo pada tahun 1964 bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang diejawantahkan menjadi mengembalikan kembali hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya dirinci kembali dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, bahwa tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam pasal 3, disebutkan sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Melihat kondisi yang ada dan menilik UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, menurut saya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam rangka memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan. Pertama, mengubah mindset masyarakat. Salah satunya dengan cara desiminasi terkait pemasyarakatan. Para petugas pemasyarakatan harus masuk ke institusi terkecil dalam masyarakat yaitu pada tingkat RT di mana banyak sekali kegiatan di tingkat RT yaitu pengajian, arisan, dasawisma, rapat RT, dan lain sebagainya. Petugas pemasyarakatan bisa masuk pada kegiatan warga tersebut untuk memberikan sosialisasi mengenai pemasyarakatan dengan tujuan agar warga mempunyai pemahaman yang benar terkait pemasyarakatan.
Kedua, percobaan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini diperuntukkan kepada narapidana dengan lowrisk (tentunya yang sudah di-assesment oleh petugas pemasyarakatan) yang mempunyai kemungkinan melarikan diri sangat kecil. Karena kegiatan ini akan menghubungkan secara langsung narapidana dengan masyarakat luar lembaga. Maka dari itu, kegiatan ini mengharuskan narapidana didampingi oleh petugas-petugas pemasyarakatan dalam membaur dan membantu kegiatan masyarakat.
Bentuk kegiatannya seperti pembersihan dan pengecatan tempat ibadah seperti masjid dan gereja, ikut membersihkan jalan-jalan kampung, pemasangan tempat sampah hasil karya narapidana di jalan-jalan kampung dan ikut gotong royong warga dalam membangun rumah warga atau fasilitas publik di kampung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan kembali narapidana kepada masyarakat. Dengan mambaur dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, diharapkan narapidana nantinya setelah bebas tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga tidak lagi canggung dan dengan cepat mau menerima keberadaan mantan narapidana.
Ketiga, kerjasama dengan stakeholder. Petugas pemasyarakatan bisa bekerjasama dengan NGO, LBH, yayasan, perusahaan, pemilik usaha, universitas, institusi pemerintah terkait, lembaga pendidikan informal non formal, dan kelompok-kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan akan sangat terbantu dengan adanya stakeholder terkait baik pada saat pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan pada saat narapidana mendapat program asimilasi dan integrasi (dalam hal ini yang melakukan pembinaan adalah pihak balai pemasyarakatan). Bentuk kerjasama bisa mulai dari pembinaan kepribadian (berbuhungan dengan mental keagamaan dan konseling), pembinaan kemandirian (berhubungan dengan ketrampilan dan minat bakat), pengawasan, advokasi, fasilitasi, dan pengembangan diri.
Kalau ketiga hal tersebut bisa berjalan selaras dan ditambah dengan revitalisasi peran petugas pemasyarakatan beserta stakeholder pemasyarakatan yang saling bahu membahu, bukan hal yang mustahil mantan narapindana akan memiliki masa depan yang cerah. Semoga.
Artikel Lainnya
-
160526/04/2020
-
170727/03/2020
-
56628/11/2024
-
Petani, Jokowi dan Ketahanan Pangan
145610/06/2021 -
Pasca Demostrasi, Berpijaklah Pada Filsafat Konkret Gabriel Marcel !
13302/10/2025 -
Menghadapi Quarter Life Crisis
87613/06/2021
