Byung-Chul Han: Eros Online dan Gairah Selfi
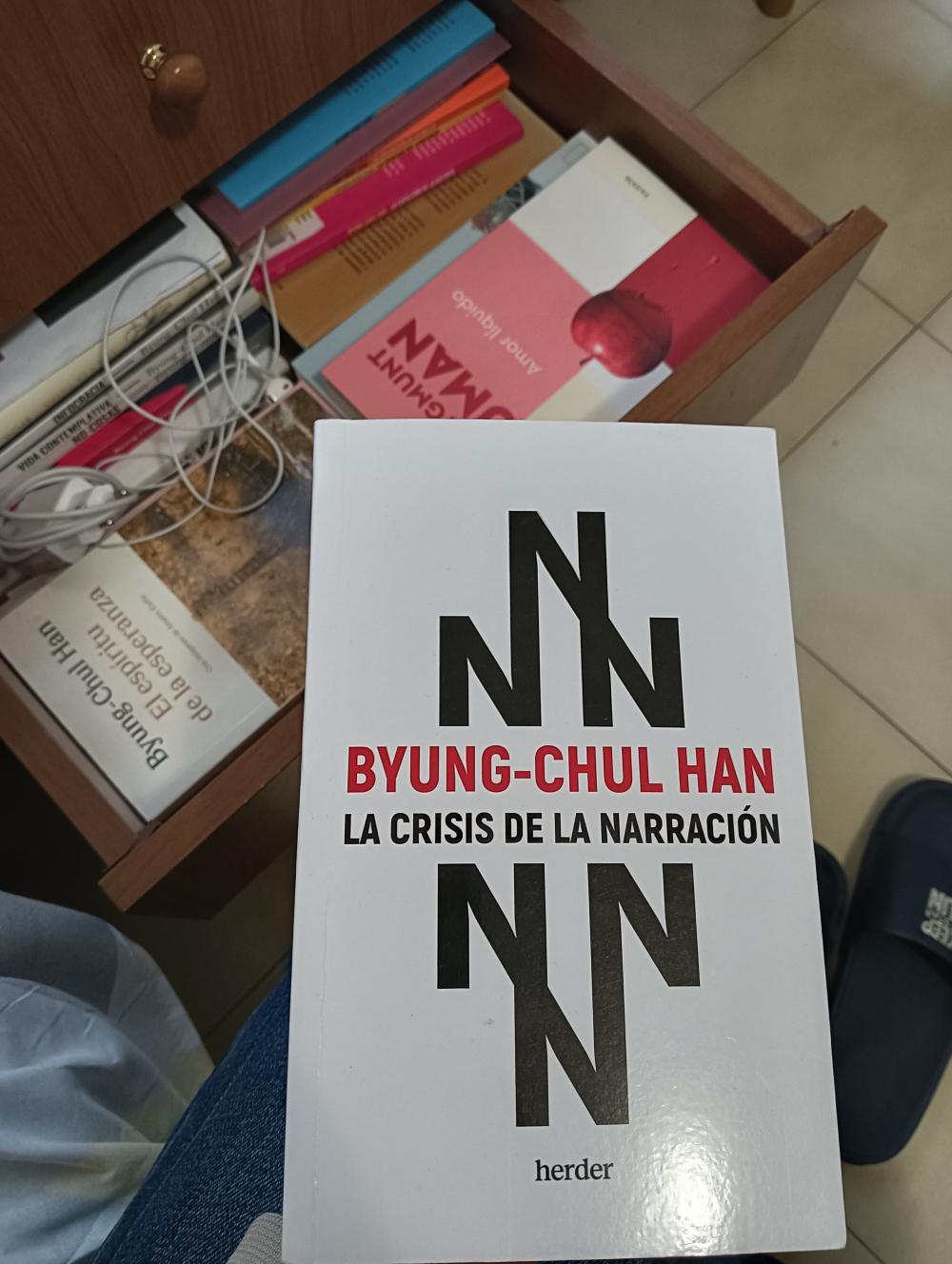
Selfie Ergo Sum adalah motto homo digital kontemporer. Alih-alih menyempurnakan diri, justru aku selfi, Sum makin tinggi? Ataukah sebaliknya makin aku berusaha menjadi yang autentik, Sum justru makin autoeksploitasi, dan autodestruksi.
Semua selfi itu paradoks, tidak magis, dan antimetafisis. Selfi menolak autentisitas. Selfi membuat subjek menjadi yang lain, yang kaku, yang beku, dan yang spontan. Yang lain di sini tidak berarti menjadi sama seperti orang lain, baik wajah, muka, karakter, sifat, sikap, pemikiran maupun personalitas. Akan tetapi aktus selfi membuat subjek harus melampaui diri, dan menipu diri. Selfi tidak suka dengan keindahan, kecuali kecantikan: semua selfi bisa cantik, tetapi tidak indah, dan bukanlah yang indah.
Selfi memang cantik tetapi tidak berbicara banyak tentang realitas. Ia menangkap sebagian kecil realitas yang dihentikan, dan yang dimiskinkan. Ia mengerutkan makna kebertubuhan, dan keindahan tubuh. Di hadapan kamera selfi, subjek tidak bisa merayakan kebertubuhannya, karena subjek hanya menunjukkan muka yang miskin ekspresi dan menyembunyikan sebagian besar anggota tubuh. Menyembunyikan sebagian besar anggota tubuh berdampak pada penolakan terhadap diri sendiri. Hal ini tampak ketika subjek hanya sibuk merias muka dan bagian kepala, tetapi membiarkan tubuh lainnya kusuk, dan tertekan. Di balik kecantikan senyuman hasil selfi, ada banyak anggota tubuh yang ditekan, ditolak, dikucilkan.
Selfi tidak ingin abadi. Dari sekian banyak aktus selfi, hanya satu atau dua yang hasilnya baik, sedangkan yang lainnya dihapuskan dari galeri! Yang baik akan disimpan. Selfi yang disimpan tidak memiliki makna keterwakilan dari manusi di balik itu: kehadirannya dimiskinkan. Byung-Chul Han berpendapat bahwa selfi “bukanlah suatu emanasi, melainkan suatu eliminasi dari objek. Ia tidak memiliki hubungan intens, intim dan libidinal dengan objek. Ia tidak mendalam, tidak tergoda dengan objek. Ia tidak memanggilnya, tidak berdialog dengannya. Kecerdasan buatan menghasilkan suatu realitas baru yang diperluas yang tidak ada¸ suatu hiperrealitas yang tidak menjaga korespondesi dengan realitas, dengan objek real. Fotografi digital adalah hiperreal.”
Selfi menunjukkan ketidakhadiran, yang hanya menampilkan realitas yang kering tanpa menimbulkan kejutan dan kekaguman. Selfi melupakan momentum dari peristiwa dan sejarah karena ia temporal belaka. Selfi muda tua dan kedaluwarsa. Hal ini dikarenakan “selfi”, menurut Byung-Chul Han, “adalah muka yang dipamerkan tanpa aura. Ia mengurangi keindahan ‘melankolik’. Ia dicirikan oleh kebahagiaan digital. Selfi-selfi, yang adalah informasi, hanya mempunyai makna di dalam komunikasi digital. Mereka menyembunyikan kenangan, takdir dan sejarah.” Ketemporalan selfi berkaitan erat dengan watak manusia seperti narsistik, toksik, dan perfeksionis.
Ponsel cerdas mengintensifkan selfi. Sekarang ini tidak sedikit orang yang narsistik, toksik, dan perfeksionis. Orang-orang seperti ini dilanggengkan oleh selfi. Selfi bertolak belakang dengan autentisitas. Pada abad ini tidak sedikit orang ingin menjadi yang autentik. Menjadi yang autentik di tengah rezim kapitalisme neoliberal menimbulkan paradoks. Alih-alih menjadi yang autentik, sesorang justru terjebak narsistik, toksik dan perfeksionis. Terjebak? Siapa yang menjebakkan subjek? Subjek sendiri yang menjebakkan diri, karena ia berupaya menjadi yang lain dari dirinya. Apakah yang narsistik, toksik dan perfeksionis tidak autentik? Ini akan dijawab pada penjelasan selanjutnya, bagaimana hubungan antara autentisitas, autoproduksi, autoeksploitasi, dan auto-destruksi.
Masyarakat saat ini sedang dikendalikan oleh prinsip autentisitas. Manusia taat di bawah perintah menjadi yang autentik, dengan kata lain, menunjukkan perbedaan dari yang lainnya. Byung-Chul Han menekankan bahwa “diskursus autentisitas diubah menjadi alat yang efektif dari autoeksploitasi. Di balik perasaan autentisitas, manusia membangun dirinya dalam hubungan autodestruksi. Keinginan menjadi yang autentik berubah menjadi semacam algojo. Ambisi menjadi autentisitas menghilangkan apa yang kolektif atau yang publik.”
Semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Diselimuti oleh ambisi autentisitas bahwa harus melihat dengan kesanggupan autorealisasi. Autentisitas mempunya misi “menjadi setia pada diri sendiri”, dan membongkar belenggu masyarakat. Ini dapat dimengerti sebagai bagian dari proyek individualisasi: kontrol sosial menjadi belenggu baginya, yang membuat dia tidak bebas, tidak autentik. Byung-Chul Han berpendapat bahwa “kultus menjadi autentisitas menggantikan persoalan identitas dari masyarakat sampai tingkat persona individual. Dipekerjakan secara permanen dalam produksi diri sendiri. Dengan cara ini, kultus autentisitas mengatomisasi masyarakat.”
Bagi Byung-Chul Han, autentisitas “berarti sudah dibebaskan dari pola ekspresi dan perilaku yang dikonfigurasi sebelumnya dan dipaksakan dari luar. Darinya timbul perintah menjadi sama hanya dengan dirinya sendiri, dalam mengartikan diri sendiri semata-mata oleh diri sendiri, lebih dari itu, menjadi penulis dan pencipta bagi diri sendiri.” Autentisitas mengembangkan tekanan kinerja atau melampauinya, dalam pengertian ini, subjek autentik ditemukan ditundukkan oleh perintah neoliberal “dapat-melakukan”. Kekerasan terhadap diri sendiri ini tidak menemukan perlawanan, yang pada dasarnya, ditemukan dalam kebebasan. Tindakan ini bukanlah tugas dari luar, melainkan “dapat-melakukan” seperti sensasi autentisitas, yang dicirikan dengan diskursus ketundukan.
Byung-Chul Han mengatakan “imperatif autentisitas memaksa diri memproduksi diri sendiri. Dalam istilah terakhir, autentisitas adalah bentuk neoliberal dari produksi diri. Ia mengubah setiap orang menjadi produser diri sendiri. Diri sebagai pengusaha itu sendiri diproduksi, direpresentasi, dan ditawarkan sebagai komoditas. Autentisitas adalah sebuah argumen nilai jual.” Subjek ditemukan ditundukkan pada kekerasan oleh autentisitasnya. Dengan demikian, tindakan “mengeksploitasi diri”, sesungguhnya, adalah menghancurkan diri. Namun, kelebihan memproduksi diri sendiri, menghancurkannya.
Autentisitas bertolak belakang dengan autoproduksi, autoeksploitasi, dan autodestruksi sebagai akibat dari narsistik, toksik, dan perfeksionis justru membuat subjek mudah stres, kecemasan yang berlebihan, kegelisahan, dan depresi yang parah. Lebih tepatnya, autentisitas adalah musuh abadi dari narsisime, toksisme, dan perfeksionisme. Keheningan dan ketenangan tidak dapat melerai dan mendamaikannya. Doa, meditasi, dan kontemplasi tidak dapat mengadilinya. Kecanduan selfi justru mengintensifkannya. Inilah paradoks selfi.
Selfi tidak hanya mengintensifkan watak narsistik, tetapi juga melestarikan kegelisahan, dan depresi karena subjek tidak pernah mencapai titik kepuasan dan penerimaan diri sebagaimana adanya. Ada yang lebih berbahaya dari kecanduan selfi: Ketika kematian dianggap sebagai nasib dan kewajaran yang tidak perlu ditangisi, yang tidak harus merasa kehilangan, dan tidak perlu merasa duka. Kita juga menemukan dukacita digital ketika ada orang yang mengunggah foto-foto dari sesorang yang sudah meninggal dengan lingkaran di keliling kepala, dan caption dukacita digital.
Byung-Chul Han menegaskan bahwa “selfi menunjukkan hilangnya persona yang didakwa dalam takdir dan sejarah. Ia mengekspresikan cara hidup yang dengan gamblang menyerah pada saat ini. Selfi tidak mengenal duka cita. Kematian dan kefanaan jauh. Selfi pemakaman menunjukkan tidak adanya duka cita. Di sebelah peti mati, orang-orang tersenyum bahagia ke arah kamera. Mereka mendongkolkan kematian dengan ironis keakuan. Akan tetapi kita juga dapat menyebut ini sebagai dukacita digital.”
Selfi adalah salah upaya subjek untuk menghibur diri dan mengabadikannya tetapi ia lupa bahwa makin ia narsistik, ia justru makin tidak autentik. Ketika subjek tidak autentik, ia tentu tidak bisa abadi. Yang abadi adalah kecanduan selfi. Alih-alih “merasa bisa abadi” dalam autentisitas, ia justru terjebak dalam narsisisme digital. Narsisisme digital tidak lain adalah duka cita digital. Apakah aku selfi maka aku ada?
Aku ada untuk menjadi aku yang berguna bagi diri dan semuanya. Kalau aku ada hanya berguna untuk diri sendiri, aku terjebak dalam narsisisme, toksisme, dan perfeksionisme. Aku ada kalau aku masih memiliki rasa empati, simpati, suka cita dan duka cita kemanusiaan. Kalau aku tersenyum bahagia di hadapan penderitaan, kemalangan, kejahatan, peperangan, dan kematian, sesungguhnya aku sudah tidak ada.
Artikel Lainnya
-
73726/10/2023
-
225121/09/2021
-
80102/01/2024
-
Menghadirkan Inklusivitas Bagi Penyandang Disabilitas
199803/12/2020 -
145003/04/2021
-
Mengurai Kesalahpahaman Teori Evolusi #2: “Evolusi Hanyalah Teori yang Belum Terbukti”
52706/11/2024
