Bentuk Kepatuhan Publik di Tengah Pandemi
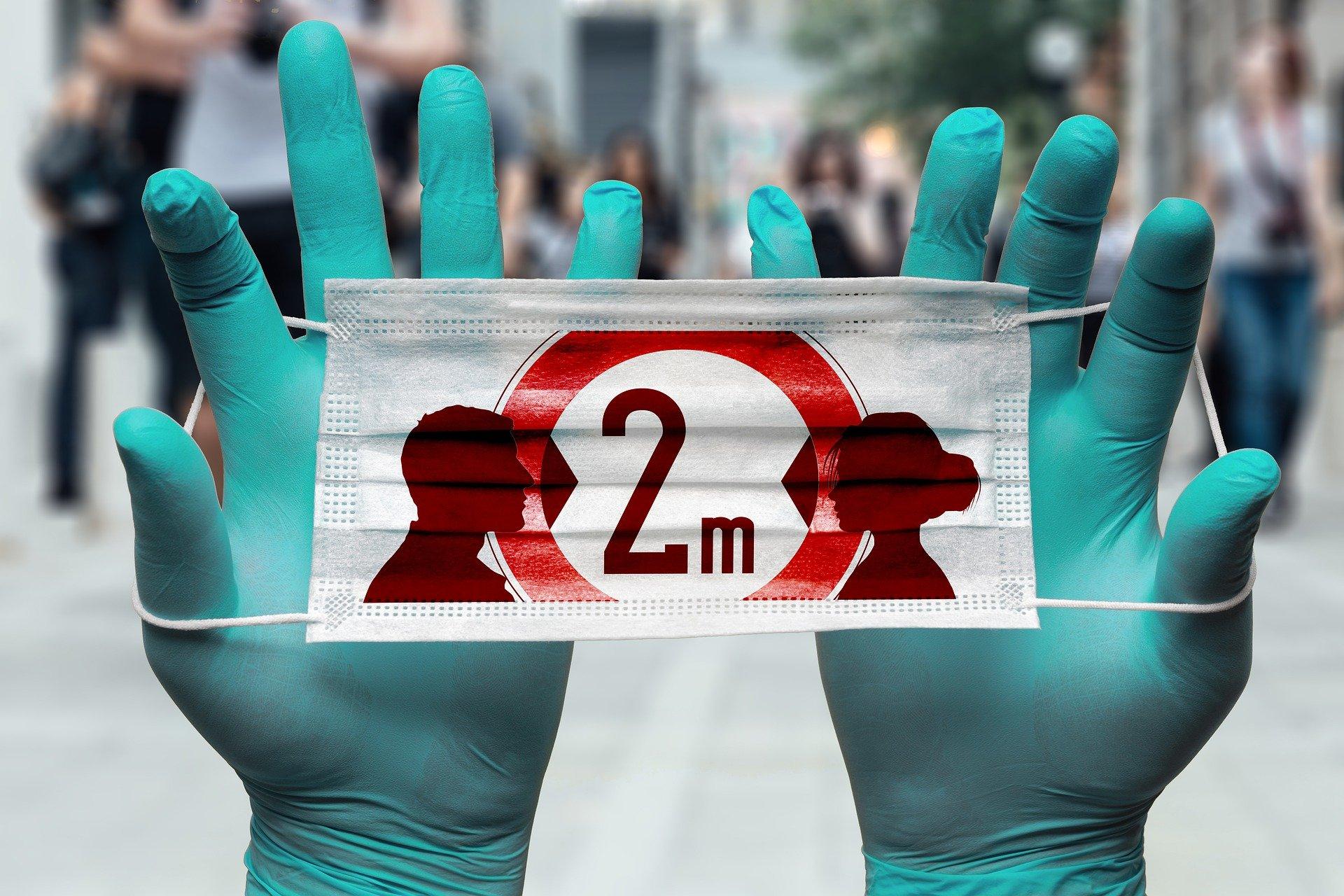
Kita sudah tahu, pandemi Covid-19 belum surut. Hemat saya, adalah sebuah tindakan pencegahan yang baik jika kita menjauhi kerumunan atau keramaian, jaga jarak dengan orang sekitar, serta tetap diam di rumah (tidak bepergian ke tempat jauh/luar daerah).
Ditambah lagi, kini sudah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika imbauan ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, nicaya penularan virus corona bisa terputus. Kesadaran untuk melaksanakan apa yang diimbau atau diinstruksikan merupakan modal utama dalam memutus mewabahnya virus ini.
Akan tetapi, pada nyatanya, masyarakat kita masih belum terlalu taat menjalankan anjuran dan imbauan tersebut. Banyak orang masih menganggap sepele dan tidak peduli dengan anjuran pemerintah. Memang cukup sulit membuat orang untuk patuh dan taat pada suatu perintah, karena dipengaruhi oleh mental dan karakter kita yang terlalu ‘masa bodoh’ dengan apapun. Saya bisa pastikan bahwa perilaku taat atau kepatuhan terhadap suatu imbauan (instruksi) khususnya dari pemerintah, bisa dibilang masih rendah.
Problem sulit taat atau tidak patuh pada peraturan dan/atau imbauan, bukan sesuatu yang baru dalam realitas sosial kita. Kalau kita bertanya kepada masyarakat, jawaban mereka sangat biasa, bahwa ketidak-patuhan mereka selalu beralasan. Memang tidak mudah menghadapi hal ini.
Akan tetapi, kita tak boleh jenuh mengkampanyekan himbauan untuk tidak keluar rumah, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan berbagai anjuran lain agar penularan virus mematikan ini tidak semakin besar.
Berkaitan dengan perilaku taat atau patuh dari masyarakat, ilmu Psikologi (Sosial) memiliki konsep yang sering digunakan untuk menjelaskannya. Pemahaman tentang kepatuhan antara lain teori obedience dan compliance.
Perbedaan Obedience dan Compliance
Persoalan kepatuhan publik secara jelas dijabarkan dalam teori dinamika kelompok dan pengaruh sosial. Kita tahu bahwa sebagai pribadi yang hidup di tengah masyarakat, dengan tata aturan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalamnya, kita memiliki seperangkat aturan untuk dipatuhi sehubungan dengan diterimanya kita dalam suatu masyarakat.
Apabila kita tidak mematuhi tata aturan tersebut, kita akan dianggap tidak patuh dan menyimpang. Ini semua terjadi karena adanya pengaruh sosial (sosial influence), di mana pengaruh sosial tersebut akan mengubah sikap, perilaku, dan persepsi orang lain. Sekurang-kurangnya ada 3 aspek penting dalam pengaruh sosial, yaitu: compliance, obedience dan conformity.
Bila diterjemahkan ke dalam kata bahasa Indonesia, baik obedience maupun compliance memiliki arti yang sama yaitu kepatuhan. Namun sebenarnya jika dimaknai secara lebih detail, obedience dan compliance memiliki arti yang berbeda.
Dalam pemahaman sederhana, compliance berarti melakukan sesuatu yang dianjurkan atau respon yang diberikan terhadap situasi dari luar subyek. J.A Mayers (2008), memberikan arti compliance sebagai suatu kesepakatan yang dibuat oleh seseorang tanpa adanya beban atau paksaan, sehingga dapat dilakukan secara tulus, tanpa merasa terbebani.
Hal ini juga didukung oleh Robert Cialdini (2007) yang mengatakan bahwa compliance merupakan suatu bentuk pengaruh sosial, dan berfokus pada kemauan seseorang untuk mengikuti, serta melakukan permintaan seseorang dengan tidak terpaksa atau ikhlas.
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa compliance merupakan tindakan seseorang yang bersedia melakukan suatu hal karena dia menyetujui sebuah permintaan dan bukan karena perintah atau paksaan dari atasan. Semisal, seorang tenaga medis (perawat), akhirnya menggunakan APD secara lengkap setelah menyetujui dan sadar bahwa APD itu akan melindunginya dari penyebaran virus.
Sementara itu, obedience menurut Stanley Milgram adalah suatu bentuk prilaku dimana seseorang mematuhi perintah langsung dari pimpinan. Obedience menjadikan seseorang melakukan perubahan sikap dan tingkah lakunya untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain tanpa membutuhkan persetujuan dari orang tersebut.
Obedience dikatakan terjadi jika seseorang mengikuti perintah atasannya tanpa mempertanyakan untuk apa perintah tersebut. Contoh kecil dari obedience, lebih banyak terjadi pada dunia anak-anak, yakni jika seorang anak diperintahkan oleh orangtuanya untuk menuruti kata-kata orang tuanya, atau menghargai orang lain yang lebih tua darinya. Atau di lingkungan sekolah misalnya, di mana seorang murid dituntut untuk menuruti perintah gurunya selama di sekolah.
Contoh sederhana dalam situasi saat ini adalah demikian; keluarga pasien akan menggunakan masker jika ada tenaga medis yang meminta atau mengontrolnya. Artinya, ia akan taat dan patuh karena ada orang lain, dan bukan dari kesadarannya sendiri.
Berdasarkan dua pemahaman tentang compliance dan obedience yang menjelaskan definisi kepatuhan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang karena adanya stimulus tertentu. Stimulus yang menyebabkan kepatuhan tersebut dapat berupa permintaan, peraturan, perintah, maupun paksaan yang akhirnya menimbulkan tindakan patuh untuk mengikuti stimulus.
Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai merupakan sebuah pilihan. Artinya individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis suatu aturan, himbauan, hukum, norma sosial, permintaan, maupun keinginan dari orang lain yang memegang otoritas ataupun peran penting (Morselli dan Passini, 2012).
Bertolak dari sini, kita sudah bisa menemukan bahwa bentuk kepatuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, sedikit banyak mengarah ke konsep obedience. Alasan sederhananya karena pada dasarnya, masyarakat kita akan lebih taat kalau diawasi atau adanya ‘power’ yang berkuasa dan memaksa. Memang, tidak semua yang seperti itu, masih ada banyak orang lain yang memang melaksanakan perilaku patuh berdasarkan konsep compliance.
Konformnitas (conformity): Pengaruh Sosial yang (mungkin) Diperlukan
Secara sadar maupun tidak, kita biasanya cenderung untuk mengikuti aturan atau imbauan yang terdapat di lingkungan sosial; seperti ketika memilih menggunakan masker kain yang dijahit sendiri, saat keluar rumah yang sama dengan orang lain dalam lingkungannya karena mengikuti imbauan pemerintah untuk ber-masker.
Padahal orang tersebut bisa saja tidak memilih menggunakan masker kain, yang sama dengan orang lain jika ia mau, tetapi ia memilih untuk mengenakan masker kain yang sama dengan orang di sekitarnya agar sesuai dengan prilaku kebanyakan orang. Hal inilah yang dikenal dengan konformitas (conformity).
Pengaruh informasi karenanya dapat dilihat sebagai proses rasional yang menyebabkan perilaku orang lain bisa mengubah keyakinan atau interprestasi kita atas suatu situasi, dan konsekuensinya membuat kita bertindak sesuai dengan kelompok itu.
Dari pemahaman ini, bisa saya katakan bahwa, konformnitas (mungkin) dapat dijadikan contoh dari bentuk patuh terhadap imbauan pemerintah agar masyarakat bisa mengikuti PSBB. Supaya masyarakat kita tidak saja ‘taat buta’ atau melakukan sesuatu karena terpaksa dan tidak memahami apa maksud dibalik anjuran itu, maka konformitas dalam dinamika kelompok sosial bisa dijadikan rujukan kepada pemerintah agar pemberlakuan PSBB bisa efektif dan efisien.
Ketika suatu kelompok masyarkat benar-benar disadarkan untuk menjalankan anjuran pemerintah (misalnya, hal menggunakan masker ketika keluar rumah/menghindari keramaian dan jaga jarak) maka sudah pasti, salah satu warga yang tinggal di dalam kelompok masyarakat tersebut, yang awalnya tidak patuh, lambat laun akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan kelompok masyarakat lain di lingkungan sosialnya. Ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kelompok masyarakat yang lebih besar.
Intinya, kekompakan dan kebersamaan harus ditingkatkan dalam satu kelompok besar, sehingga segelintir orang yang masih belum patuh, bisa tergerak dan termotivasi untuk merubah pola pikir dan perilaku, dan dapat mengikuti kebiasaan umum yang ada, khususnya berbagai anjuran pemerintah seperti; tetap tinggal di rumah, hindari keramaian dan menjaga jarak fisik, termasuk didalamnya pelaksanaan PSBB.
Sumber Bacaan :
Baron, R.A. dan Byrne, D, 1994. Social Psychology; Understanding Human Interaction. Allyn & Bacon, Inc, Boston
Cialdini, R. B. (2007). Psikologi Persuasif Merekayasa Kepatuhan. Jakarta: Prenada Media Group.
Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. The Journal of abnormal and social psychology, 67(4), 371.
Morselli, D., & Passini, S. (2012). Rights, democracy and values: A comparison between the representations of obedience and disobedience in Italian and Finnish students. International Journal of Intercultural Relations. 36, 682- 693. DOI: 10.116/j.ijintrel.2012.03.008
Artikel Lainnya
-
36426/01/2025
-
379430/04/2022
-
161823/08/2020
-
Kesadaran Berpolitik dan Pengawalan Proses Pemilu 2024
32731/12/2023 -
Hari Ibu dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
169322/12/2020 -
Whistle-Blowing: Membuka Mulut, Membongkar Pembusukan Kebenaran di Ruang Publik
184902/04/2020
