Manusia, Filsafat, dan Para Monyet yang Mengaku Telah Membunuhnya
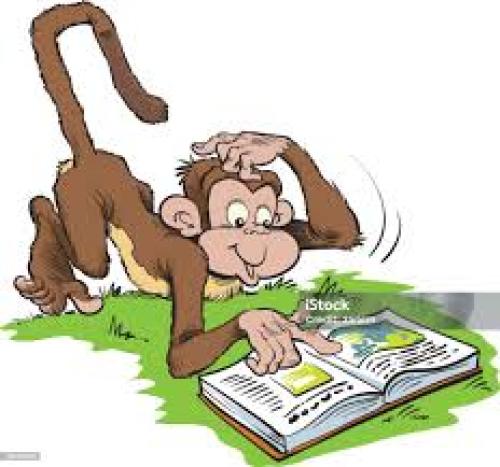
Semua manusia lahir ke dunia dengan alasan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Setiap kelahiran adalah hasil dari rentetan sebab yang panjang, terjalin dalam lingkaran karma, sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi jauh sebelum manusia sempat bertanya mengapa ia ada. Takdir yang diyakini sebagian orang dan ditolak oleh sebagian lainnya atas nama ilmu pengetahuan bukanlah jawaban akhir atas keberadaan manusia. Pertanyaan itu tetap menggantung di dada siapa pun yang berani merenung. Apa tujuan aku ada. Siapa aku. Dan apa keinginanku yang sebenarnya.
Pertanyaan seperti ini menghantarkan sang Aku pada kesunyian yang menusuk, pada perasaan terasingkan dan teralienasi dari dunia. Dalam sudut hatinya yang terdalam, ia sadar bahwa mungkin hanya dirinya sendiri yang tersisa. Manusia sering lahir dari orang tua yang belum selesai dengan luka batin mereka sendiri. Suami dan istri hidup saling menuntut pengakuan, saling membanggakan siapa yang paling berjasa dalam mempertahankan rumah tangga. Dan di luar itu, ada sekelompok monyet yang dengan pongah mengaku telah memahami esensi serta eksistensi manusia, bahkan berani menyatakan bahwa filsafat telah mati.
Betapa konyol para monyet itu. Mereka kebetulan menemukan sebuah buku yang terjatuh dari tas seorang bijak, membacanya setengah, lalu merasa telah menguasai hakikat manusia. Dengan bangga mereka mengumumkan bahwa filsafat sudah tidak diperlukan, seolah mereka telah menemukan kebenaran terakhir. Mereka seperti anak kecil yang menemukan kerang di tepi pantai dan mengira telah memahami samudera.
Mereka mengukur manusia dengan angka, menimbang jiwa dengan statistik, dan percaya bahwa kebahagiaan dapat diformulasikan melalui rumus yang rapi. Mereka lupa bahwa manusia bukan mesin yang dapat dijelaskan oleh algoritma. Manusia adalah luka yang berjalan, rahasia yang berdetak di dada, pertanyaan yang tidak pernah selesai dijawab bahkan oleh dirinya sendiri.
Sungguh menyedihkan ketika dunia kini dipenuhi oleh orang-orang yang hanya berani percaya pada apa yang bisa diukur. Bagi mereka, yang tidak bisa dihitung dianggap tidak ada, dan yang tidak bisa diuji dianggap tidak penting. Padahal justru di dalam hal-hal yang tak terukur itulah manusia menemukan dirinya yang paling manusiawi. Sebuah senyum yang muncul di tengah duka tidak bisa diukur oleh matematika. Kerinduan yang tiba-tiba datang di tengah malam tidak bisa dijelaskan oleh fisika. Rasa bersalah yang menusuk hati hingga membuat seseorang menangis seharian tidak akan pernah ditemukan dalam laboratorium mana pun.
Filsafat pernah menjadi rumah bagi pertanyaan-pertanyaan itu. Rumah yang kini sepi karena banyak orang memilih tinggal di bangunan megah bernama kepastian. Mereka lebih senang memeluk kepastian meskipun palsu daripada menghadapi kegelisahan yang jujur. Namun rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Masih ada jiwa-jiwa yang duduk di dalamnya, termenung, bertanya, dan menangis dalam diam. Dari merekalah manusia akan kembali diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mencari cara agar tetap bernapas, tetapi juga tentang menemukan alasan mengapa kita mau terus bernapas.
Pada akhirnya, filsafat tidak membutuhkan panggung besar untuk bertahan. Ia hidup di ruang-ruang sunyi, di dada orang-orang yang berani mempertanyakan makna di tengah dunia yang sibuk dengan keuntungan. Mereka yang benar-benar mengerti filsafat tidak pernah membanggakan diri sebagai ahli. Mereka justru semakin sadar betapa sedikit yang mereka ketahui, dan betapa luasnya kegelapan yang belum terjamah oleh cahaya pemahaman manusia.
Mungkin hanya mereka yang berani merasa bodoh, yang mau mengakui bahwa dirinya tidak tahu, yang benar-benar pantas disebut manusia. Karena manusia yang paling manusiawi adalah manusia yang sadar bahwa keberadaannya sendiri adalah misteri yang tak pernah selesai. Dan selama kesadaran itu ada, filsafat akan terus bernapas, meskipun para monyet itu terus berteriak bahwa mereka telah berhasil membunuhnya.
Mereka boleh terus memamerkan gelar, menghitung angka, dan menertawakan kegelisahan manusia. Mereka boleh membangun menara kepastian setinggi langit, menuliskan rumus demi rumus yang mereka kira telah merangkum seluruh rahasia semesta. Namun setiap kali seseorang terbangun di malam yang sunyi dengan dada sesak tanpa sebab, filsafat kembali berbisik. Setiap kali seseorang menangis di sudut kamar karena rindu yang tak bisa dijelaskan, filsafat membuka matanya. Setiap kali seorang manusia berdiri di tepi jurang dan bertanya mengapa ia harus terus hidup, filsafat kembali bernapas.
Dan itulah yang tak akan pernah dipahami oleh para monyet itu. Mereka bisa mengatur segala hal di luar, tetapi tidak akan pernah mampu menjangkau ruang terdalam manusia, ruang yang tak bisa disentuh oleh alat ukur mana pun. Mereka lupa bahwa manusia tidak hanya terdiri dari daging dan angka, tetapi juga kegelisahan yang abadi.
Selama manusia masih bertanya, filsafat tidak akan mati. Selama ada satu orang saja yang berani duduk sendirian dan menatap ke dalam dirinya dengan jujur, selama itu pula filsafat akan hidup, sekalipun dunia menertawakan dan menuduhnya gila. Karena filsafat bukan tentang jawaban yang pasti, melainkan tentang keberanian untuk terus bertanya meskipun jawaban itu tak akan pernah sepenuhnya ditemukan.
Dan mungkin, hanya manusia yang rela memikul kegelisahan seperti itulah yang benar-benar hidup. Sisanya hanyalah tubuh yang bergerak, boneka yang berjalan mengikuti arus, yang percaya bahwa angka dan kepastian adalah kebenaran terakhir. Biarkan saja mereka, karena pada akhirnya, bahkan para monyet itu akan menemukan saat ketika matematika tak bisa lagi menjelaskan rasa sakit di dadanya sendiri. Pada saat itu, filsafat akan tersenyum tipis, menunggu mereka kembali dengan malu, untuk pertama kalinya belajar bertanya seperti manusia
Artikel Lainnya
-
108407/02/2023
-
9327/06/2025
-
161024/07/2020
-
119607/06/2020
-
160611/10/2020
-
Regenerasi Petani Menuju Indonesia Emas
181509/04/2024
