Krisis Narasi dan Sastra sebagai Metode
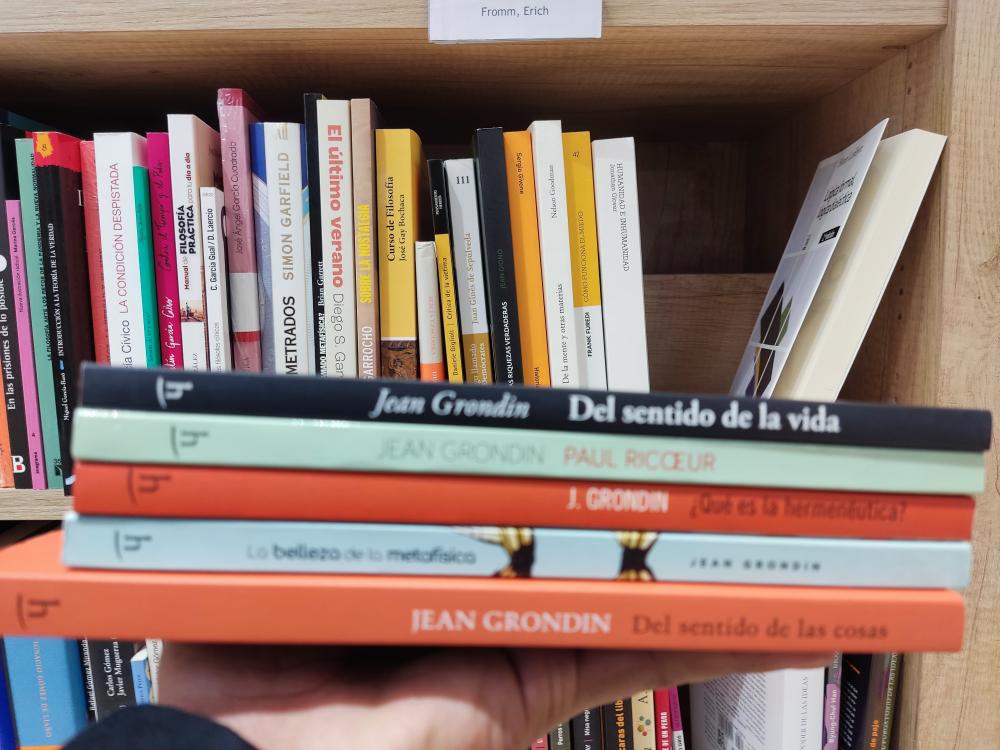
Sebelumnya katastrofe selalu dikaitkan dengan bencana alam semesta. Namun beberapa dekade terakhir katastrofe berkaitan dengan akibat kebijakan politik rezim yang mengancam secara tiba-tiba kesejahteraan, kebebasan, kesehatan dan kebahagiaan rakyat. Rezim pemerintah menggalakkan politik peralihan isu, dan membalikkan fakta. Semua awak media, media dan rakyat mengalihkan perhatian politisnya dari yang urgen dan aktual menuju yang antik, sensual, provokatif, dan sensitif. Rezim pemerintah mempermainkan emosi media dan rakyat dengan meningkatkan jumlah informasi. Tim buzzer politik dengan buzzed-up mengaduk-aduk hasrat konsumeristis rakyat akan informasi dengan bantuan algoritma teknologi. Algoritma menguasai dan mengendalikan seluruh isu politik dan hasrat konsumeristis rakyat.
Kelebihan informasi adalah krisis berita dan narasi pada era serba digital ini. Informasi buklanlah berita, apalagi narasi. Tiap hari rakyat internet dibanjiri informasi yang hanya memuat intensi pasar kapital. Informasi digital menyebar lebih banyak sampah daripada isi. Informasi-informasi membuat kepala putar-putar karena banyak yang dipikirkan (mind is buzzing). Kelimpahan informasi meningkatkan krisis berita dan krisis narasi. Sementara krisis berita mengemukakan krisis jurnalis, etika jurnalistik, dan kode etik jurnalistik, krisis narasi menjelaskan krisis narator (storyteller), dan narasi yang disimulakrakan.
Pasca-narasi
Kita memasuki era pasca-narasi di mana sampah-sampah informasi yang anti-historis menguasai kepala kita. Narasi disulap menjadi informasi belaka. Narasi hanya dilihat sebagai peristiwa masa lalu yang tidak penting untuk dipelajari, dinterpretasi, dipertimbangkan dan diaktualisasikan (sejauh perlu dan mendesak) saat ini. Sesungguhnya narasi yang kehilangan ciri historisnya bukanlah narasi, melainkan informasi. Narasi memiliki alur kisah yang jelas—entah maju, mundur, dan campuran keduanya—dan mempunyai kesimpulan yang jelas. Sementara itu informasi menghapus alur, karena yang terpenting adalah seberapa jauh ia dibaca, emosi dan pikiran dipermainkan, dan dengan demikian, semakin banyak nilai lebih (uang/profit) yang didapatkan. Byung-Chul Han dalam por favor, cierra los ojos. A la búsqueda de otro diferente (2016: 10-11) berkomentar: “Informasi bukanlah wacana kata. Itulah sebabnya ia cenderung berkembang biak (proliferar) dan menjadi (makin) masif (masificarse). Dalam hal ini ia dibedakan dari pengetahuan seperti dari pengetahuan dan kebenaran.”
Kalau narasi mereproduksi dan mendekonstruksi makna kehidupan, informasi justru mematikannya. Kalau narasi meningkatkan mutu dan nilai kemanusiaan dari penghayatan keagamaan, adat istiadat, dan kebudayaan, informasi mementahkannya. Kalau narasi meruncing dan mempertajam kreativitas imajinasi, informasi justru mengendalikannya. Kalau narasi menghidupkan kembali dan memberi makna terhadap teks-teks lisan di dunia-kehidupan, informasi justru mengakulasikan dan menghitungnya sebagai bahan mentah kapital. Kalau narasi tegar merawat dan menimba nilai-nilai luhur di balik dunia-makna estetika, metafisika, dan supranatural dari tubuh manusia, informasi justru menelanjangkan dan menyebarkannya secara bebas di media sosial. Byung-Chul Han dalam la crisis de la narración (2023:55-56) berkomentar: “Krisis aktual tidak terpusat ´hidup atau bercerita´, tetapi pada ´hidup dan mengunggah´” di media sosial.
“Hidup dan mengunggah” ke media sosial tampak dalam kecanduan selfi. Bagi Byung-Chul Han, “Kecanduan selfi tidak mengemukakan narisisme, tetapi kekosongan batin yang menyebabkan kecanduan itu”. Saya selfi maka saya ada. Kecanduan selfi mengemukakan, aku hidup di mana-dengan siapa-berbuat apa di sini kini mesti diketahui oleh semua rakyat digital di media sosial. Byung-Chul Han menyebut itulah kondisi terkini masyarakat informasi dan transparansi, di mana “Di hadapan kokosongan batin, ego (el yo) menciptakan citra dirinya sendiri dan mementaskan-nya secara permanen. Selfi mereproduksi bentuk diri yang kosong.” Dengan demikian ego yang selfi adalah informasi yang tidak punya isi.
Pada era hiper-selfi ini informasi tidak pernah tersembunyi di balik jaringan teknologi, sebaliknya, ia justru mempromosi diri, bahkan dengan telanjang. Karena dengan keadaan telanjang yang rutin disebarluaskan, ia bisa laku di dunia pasar. “Informasi seperti itu”, kata Byung-Chul Han, berciri “pornografis, karena tidak memiliki pembungkus”. Tubuh dilihat seperti informasi pornografis, bahkan yang paling intim dari relasi kesalingan-setimpal dua tubuh teologis pun direkam, dan disebarluaskan di media sosial—baca: “Mengapa Orang Merekam Hubungan Seksual Mereka?” dalam Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/16/mengapa-orang-merekam-hubungan-seksual-mereka?open_from=Search_Result_Page. Tubuh teologis yang diubah menjadi informasi pornografis ini merupakan satu cara hidup yang tidak manusiawi, tidak sastrawi.
Sastra: Metode Hidup
Informasi bukanlah seni menceritakan, melainkan seni mempersuasi. Informasi memancing sensasi, narasi memberi arti. Narasi yang paling elegan dan tahan zaman tampak dalam karya-karya sastra. Sastra sebagai metode hidup yang paling tua. Sebelum mengenal tulisan dan teks, manusia mengandalkan ingatan untuk merekam dan mengingat setiap peristiwa. Teks-teks lisan dunia-kehidupan zaman yang direkam dan diingat dalam pikiran direproduksi dan didekonstruksi terus-menerus tanpa mencacatkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Banyak mitos, teks-teks Kitab Suci, dan karya-karya sastra yang pada awalnya dinarasikan secara lisan dari mulut ke mulut dari kampung ke kampung sampai ke tingkat dunia, masih terus bertahan sampai kini. Ingatan manusia setua dan sekuat sejarah manusia. Sementara itu, informasi, foto, selfi, gambar, video dan quotes yang disimpan di dalam kartu memori, chip, microchip atau cloud lebih rentan hancur dan hilang. Kartu memori, chip, microchip atau cloud tidak mempunyai kemampuan untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memutuskan sesuatu, karena mereka tidak produktif dan kreatif.
Hidup yang menarasikan berarti juga mendengarkan. Narator yang berhasil adalah dia yang mendengarkan dengan baik. Mendengarkan berarti belajar memahami dan berdiskursus serta menemukan kembali makna yang sempat tenggelam dalam tumpukan ingatan. Sokrates menasihati: “Habiskan waktu kosong yang kamu miliki dalam hidupmu untuk mendengarkan diskursus; dengan demikian akan memudahkan kamu memahami apa yang orang lain sulit mendapatkannya”. Telinga yang mendengarkan adalah pintu masuk kebijaksanaan. Tidak hanya itu sastra memungkinkan seseorang dengan imaji-kreatif, dan spekulasi yang dekonstruktif mengembalikan narasi-narasi lisan yang bersebaran ke dalam teks-teks tertulis. Di sini sastra tidak hanya bertujuan menyalin realitas, tetapi mendekonstruksikannya dan menyisipkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai keutamaan di dalamnya.
Sastra tidak melihat kejahatan kemanusiaan sebagai kejadian lumrah, tetapi terlibat untuk membebaskan sambil merekonsiliasi, dan menegaskan kembali martabat manusia. Berbeda dengan informasi, sastra menawarkan kepada kita bentuk tertinggi dari epistemologi ilmu pengetahuan yakni mengenal dan memahami. Sastra menyajikan kita bentuk wasana kata yaitu tidak hanya mengenal dan memahami sesuatu/seseorang sebagaimana apa adanya, tetapi menyibak ada apa di balik yang terselebung, membuatnya mudah dipahami, dijelaskan, dan dengan demikian bermakna bagi kehidupan. Dan tindakan itu tidak hanya terbatas pada ruang ontologis dan epistemologis, tetapi juga etis-aksiologis. Ketiganya berkaitan dengan aspek eskatologis dari roh manusia.
Berbeda dengan informasi, sastra memiliki roh yang dapat menelusuri misteri terdalam batas-batas imajinasi manusia. Roh sastra yang menarasikan, mengetuk nurani kemanusiaan, membongkar setiap praktik kejahatan di ruang abstrak. Apabila informasi melumrahkan kejahatan, sastra mengutuknya dengan senjata bahasa yang adalah bahasanya. “Sastra”, demikian kata Susana Onega Jaén, profesor di Universitas Zaragosa, Spanyol (Diario del AltoAragón, 9/2/2021), “Tidak hanya menghibur, tetapi juga digunakan untuk mengatasi hal-hal yang sulit ditangani” secara akal sehat.
Sastra sebagai metode hidup tampak nyata dalam upaya: mendengarkan panggilan nurani kemanusiaan terutama dalam upaya pembebasan dan penyembuhan korban kejahatan kemanusiaan atas nama kemajuan teknologi informasi, produktivitas, dan transparansi; mempersoalkan hidup manusia; memautkan nilai-nilai fisis dan metafisis, menghubungkan keteraturan natural dan supranatural; menyembuhkan dan memulihkan dari kekejaman ingatan masa lalu yang sarat akan penderitaan; menawarkan cara baru beragama dan berkepercayaan yang lebih manusiawi; dan menarasikan secara baru hidup dan cara mengada—sebagai sebuah metode malampaui yang ada (apa yang seharusnya ada oleh siapa) dengan penuh pengharapan.
Sastra yang mendengarkan, menyembuhkan, menghibur, dan mencintai semua hanya tinggal dalam diri manusia yang bebas nilai dan luput dari tekanan kepentingan perhitungan untung-rugi profit. Manusia itu tentu saja harus mempunyai kepala dingin, hati nurani, bertelinga terbuka, bermulut terkendali, dan cepat kaki, ringan tangan.
Artikel Lainnya
-
179903/08/2020
-
487905/05/2022
-
143710/11/2020
-
Membuka Mata Batin Pewaris Pancasila
144928/06/2020 -
Netralitas dan Potensi Ancaman dalam Hubungan Sosial
56712/01/2024 -
Solidaritas Natal di Tengah Pandemi Covid-19
91427/12/2020
