Coronavirus dan Kegaduhan Sains Modern
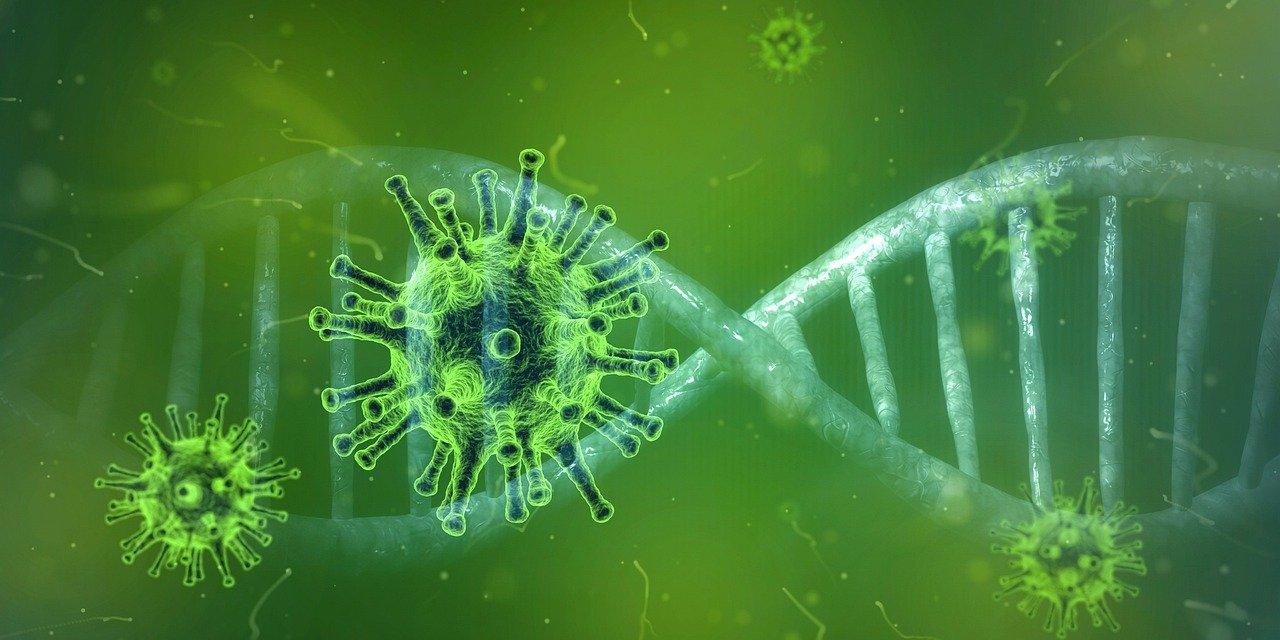
Sains telah banyak mengentaskan rasa ingin tahu manusia. Namun tidak semua keingintahuan tentang cara kerja semesta dapat terpecahkan hanya lewat dalih-dalih sains. Tentu saja ada batasnya pertanyaan yang bisa dijawab oleh sains, dan gagal memahami batas ini telah menyebabkan timbulnya kekecewaan dan kritik yang salah sasaran, tulis Donald B. Calne dalam bukunya yang berjudul Within Reason: Rationality and Human Behaviour (Pantheon Press, 1999).
Musuh-musuh sains juga menyalahkan sains dengan timbulnya kerusakan lingkungan, gas saraf, bom atom, sampai yang akhir-akhir ini sedang gaduh: covid-19 (nama ilmiah virus corona). Mereka berteori bahwa coronavirus merupakan “bioweapon yang direkayasa”.
Dilansir dari South China Morning Post pada 18 Februari kemarin, teori konspirasi tentang asal-usul virus corona sebagian besar didasarkan pada gagasan bahwa virus itu muncul dari Institut Virologi Wuhan, di mana para peneliti telah membangun salah satu basis data terbesar terkait virus kelelawar di dunia, dan merupakan yang pertama mengidentifikasi coronavirus.
Meskipun para ilmuwan berulangkali berupaya menghilangkan prasangka, teori konspirasi tentang asal-usul virus yang masih belum diketahui ini telah marak. Termasuk di Amerika Serikat, seperti yang dilansir dari The Washington Post (17/02/2020), Senator Tom Cotton merujuk ke laboratorium terkenal di Wuhan, sebuah fasilitas biosafety level-4 dengan tingkat keamanan operasional yang tinggi yang bekerja untuk meneliti patogen berbahaya.
“Sekarang kami tidak memiliki bukti bahwa penyakit ini berasal dari sana, tetapi karena bermuka dua dan ketidakjujuran China sejak awal, kita perlu setidaknya mengajukan pertanyaan untuk melihat apa yang dikatakan bukti,” ungkap Cotton dalam sebuah wawancara di Fox News’s “Sunday Morning Futures”.
Fenomena Ketakutan Sains
Diterimanya sains secara luas sebagai suatu sistem pemikiran yang mandiri merupakan peristiwa modern, tulis Donald B. Calne dalam buku yang sama. Dengan kata-kata Bertrand Russell yang ditulisnya pada 1951: “Mengingat betapa barunya sains berkuasa, tidak boleh tidak kita percaya baru berada pada awal bekerjanya sains dalam mengubah kehidupan manusia.”
Ungkapan Francis Bacon “Nam et ipsa scientia potestas est”, yang dicanangkan pada 1957, biasanya diterjemahkan sebagai “Pengetahuan itu adalah kekuasaan”, tapi ketika memasuki abad ke-21, kita bisa merumuskannya kembali sebagai “Sains itu adalah kekuasaan”. Sains telah menjadi lokomotif besar yang bisa membawa kita ke tujuan-tujuan tertentu, tapi sains tidak bisa menentukan tujuan itu.
Bahkan keberhasilan sains itu sendiri malah jadi masalah, karena hal itu telah menimbulkan harapan-harapan muluk yang tidak boleh tidak membawa kekecewaan dan berkembangnya gerakan antisains.
Fenomena ketakutan semakin intens jika kita memperhatikan perkembangan bioteknologi modern. Keberhasilan para ahli bioteknologi untuk mengembangkan sifat-sifat unggul tumbuh-tumbuhan dan binatang dapat memberikan harapan bagi manusia untuk menentukan sifat unggulnya dalam menghadapi masalah-masalah penyakit genetis.
Namun, perkembangan bioteknologi dapat pula menjadi faktor persoalan-persoalan manusia dan kegaduhan semesta. Para ilmuwan menyadari situasi paradoksal tersebut. Namun alih-alih menarik diri untuk memikirkan apa yang terbaik bagi kesejahteraan manusia pada umumnya, sang ilmuwan pun tergoda untuk mengambil resiko.
Ia mirip Sang Prometheus, seorang tokoh mitologi Yunani kuno, yang mencuri api dari kayangan dewata, figur manusia pemberani yang berkeinginan untuk mengambil resiko demi kemajuan sebagai tujuannya.
Ketakutan yang ia ciptakan ingin juga ia hadapi dengan semua resiko yang mungkin. Resiko dan harapan selalu berada dalam dirinya. Dimana ia akan mengambil resiko, di situlah ia menaruh harapan akan masa depan kemanusiaan yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, ketika ia amat sangat optimis dengan temuan ilmiah dan teknologinya di sana tersirat sebuah resiko yang tidak kecil bagi kemanusiaan.
Coronavirus: Kritik atas Pesimisme Sains
Kegaduhan sains modern dipicu oleh sikap pesimisme dalam tubuh sains itu sendiri - ilmuwan melawan ilmuwan, teknologi melawan teknologi, teori melawan teori. Terkadang pemikiran bagus seorang ilmuwan sekalipun tidak dipahami atau tidak diterima oleh orang lain. Hal ini bisa menghambat perkembangan sains, tapi hanya untuk sementara.
Pada 1879 Marquis Sautola, seorang arkeolog amatir terkemuka, menemukan lukisan-lukisan gua yang luar biasa di Altamira. Secara pribadi ia menyebarkan berita penemuannya itu dan segera saja dicap sebagai penipuan.
Ia tidak hanya dilarang membawakan penemuannya itu dalam kongres-kongres internasional mengenai arkeologi, tapi juga dicegah untuk menghadiri kongres-kongres itu, lalu meninggal pada 1888 karena kecewa. Baru pada 1903 ada rekannya yang bertekad memeriksa cerita itu dan membuktikan bahwa lukisan-lukisan tersebut memang berasal dari manusia purba dan bukan hasil tipuan di zaman modern.
Contoh lain, Artikel Krebs tentang siklus asam citric, mungkin artikel yang paling penting dalam biokimia modern, semula ditolak oleh para ahli untuk dinilai.
Dan yang paling menghebohkan adalah rumor tentang penemu coronavirus di tengah kepanikan masyarakat akan pandemik tersebut. Dilansir dari CNBC Indonesia pada 30 Januari 2020, virus corona pertama kali ditemukan oleh ahli virus di Rumah Sakit Dr Soliman Fakeeh, Arab Saudi, yang bernama Ali Muhamed Zaki pada Juni 2012.
Untuk mengingatkan ilmuwan lain, Zaki mengunggah catatannya dalam proMED, sebuah sistem pelaporan internet yang dirancang untuk secara cepat berbagi perincian penyakit menular dan wabah dengan para peneliti dan lembaga kesehatan masyarakat. Sayangnya, akibat hal itu, ia malah dipecat dan diberhentikan.
Contoh-contoh ini, tentang sains yang gagal, menimbulkan kekecewaan, tapi itu bukan berarti bahwa sains cacat dari sananya; hanya saja para ilmuwan dengan dalih-dalih ilmu pengetahuan mereka sendiri, bisa begitu terlena dalam sikapnya sendiri. Ini memberi gambaran tentang apa itu sains dan apa yang dikerjakannya.
Perkembangan ilmu pengetahuan seakan-akan ditentukan oleh kontrol yang diberikan oleh ilmuwan lain yang secara konkret menentukan apakah sebuah makalah ilmiah pantas diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Hanya kontribusi yang dipandang plausible oleh masyarakat ilmiah dapat dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah.
Kita menyaksikan bahwa plausibilitas nilai ilmiah sebuah kontribusi seringkali tidak ditentukan oleh kepastian dan realibilitas, tetapi juga oleh apakah sumbangan tersebut memiliki relevansi sistematis dan menarik perhatian.
Karena itu di balik pengakuan atas otoritas-otoritas ilmuwan justru terjadi perbedaan-perbedaan kreatif. Atau, dengan kata lain, di balik tekanan-tekanan institusi ilmiah atas kontribusi-kontribusi ilmiah, otoritas ilmiah yang sama justru memberikan penghargaan yang besar pada gagasan yang secara tajam memodifikasi pandangan-pandangan yang sudah diterima masyarakat ilmiah.
Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies volume 1 (Routledge and Kegan Paul, 1966) menekankan pentingnya manfaat kritik terhadap diri sendiri (self-criticism) ini: “Sejarah sains, seperti sejarah semua pemikiran manusia, merupakan sejarah mimpi-mimpi yang tak bertanggungjawab, sejarah sifat keras kepala, sejarah kesalahan. Tapi sains adalah satu di antara sedikit sekali kegiatan manusia, boleh jadi satu-satunya, dimana kesalahan dikritik secara sistematis dan cukup sering diperbaiki pada waktunya.”
Terhadap kasus coronavirus, ilmuwan sebenarnya harus melihat bahwa tugasnya terutama tidak hanya sekadar mencari bukti atas hipotesis yang dibangun, tetapi terlibat mencari bukti-bukti negatif untuk mendapat kepastian atas hipotesis-hipotesis baru tersebut. Ketika semua pihak sibuk saling tuduh atas kekacauan pandemik tersebut, sains lengah mencari jalan keluar. Virus terus menyebar.
Artikel Lainnya
-
110315/01/2021
-
1369106/12/2020
-
73618/12/2022
-
Catatan Redaksi: KLB Demokrat dan Senjata Virtual Kubu AHY
146214/03/2021 -
Komunisme: Jualan Politik Hari Ini
103328/06/2020 -
Collaborative Governance untuk Lawan Corona
356317/05/2020
