Mengapa Oligarki Mempecundangi Negara
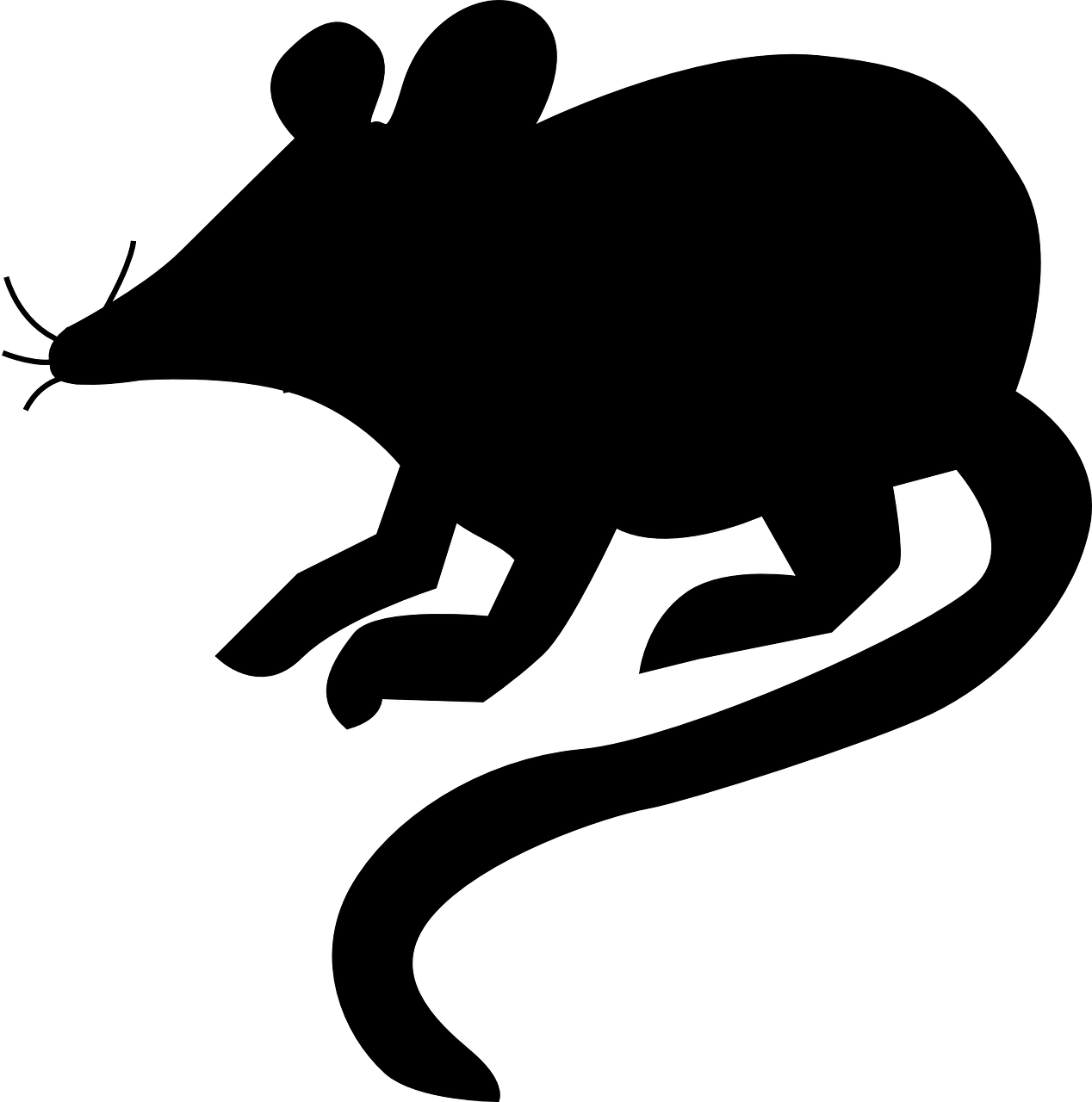
Cendekiawan Marxis, Rosa Luxemburg, mengatakan negara akan menjelma menjadi negara kapitalis manakala politik kenegaraan dimenangkan faksi kapitalis. Ini mendatangkan implikasi yang kompleks dan multidimensional mulai dari aspek struktural, kelembagaan hingga personalia. Ketiga aspek ini direkonstruksi sedemikian rupa sehingga tampak senafas dengan kepentingan akumulasi dan sentralisasi kapital yang akhirnya bermuara pada lahirnya ketimpangan.
Konsekuensi logis dari menetasnya ketimpangan adalah mengeraskan dan mempertajam relasi ketergantungan antara pihak yang memiliki kapital dengan pihak yang tanpa kapital. Kapital tidak hanya meliputi jumlah uang yang dimiliki, namun lebih dari itu adalah seluruh sumber daya yang ada dalam sirkulasi produksi kapitalis, termasuk personalia, dengan orientasi utama mengejar nilai lebih (laba). Lantas bagaimana korelasinya dengan kasus Djoko Tjandra?
Insiden pelarian buronan kakap kasus pengalihan utang cessie Bank Bali Djoko Tjandra bukan sekadar persoalan maladmistrasi, buruknya politik hukum, ataupun permasalahan keroposnya integritas aparatur birokrasi. Tetapi lebih dari itu perkara Tjandra, merepresentasikan kondisi struktural yang semakin membusuk. Tidak heran kalau elite oligarki predatorial saja – menyitir pendapat Mahfud MD, Menkopolhukam – mampu mempermalukan negara.
Betapa tidak, negara terbesar di kawasan asia tenggara dengan instrumen yang relatif lengkap, justru lumpuh tidak berdaya di hadapan Djoko Tjandra. Jangankan menangkap dan mengadili orangnya, bayangannya saja otoritas terkait gagal! Lantas di titik manakah kita (warga negara) harusnya optimis akan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di bumi pertiwi, seperti optimisme Jokowi ketika menggelar karpet merah bagi investasi, bila nyatanya aparatur penegak hukum bekerja sama dengan penjahat?
Jaringan-Aliansi Oligarki Predator
Setelah jejaknya terdeteksi pada 8 Juni 2020 lalu, buronan kakap kasus pengalihan utang cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, kembali memanas ke publik dan memantik polemik di sejumlah kalangan. Mayoritas publik dibuat heran lantaran kedatangan dan kepergiannya berlangsung mulus, tanpa ada kendala yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan oknum pejabat yang turut memuluskan modus operandi dari sang buronan tersebut.
Artinya preseden buruk ini merupakan suatu keajaiban luar biasa di tengah ancaman Covid-19 ketika oknum pejabat, utamanya penegak hukum, berkoalisi dengan Oligark predator, alih-alih menegakkan keadilan. Kendati akhirnya oknum itu telah dicopot dari jabatannya, tetapi sanksi tersebut tidak lantas membersihkan coretan di atas kertas.
Kita patut mencurigai apakah terdapat gratifikasi dalam perkara ini atau tidak. Sebab mustahil buronan kakap seperti Djoko Tjandra hanya bermodal ucapan terima kasih pada oknum pejabat yang turut membantunya. Otoritas terkait wajib melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini dengan tidak berhenti hanya pada persoalan gratifikasi maupun keterlibatan oknum pejabat. Tapi yang tidak kalah penting adalah mengungkap dalang yang lebih besar di balik itu semua.
Secara politik, memang pribadi Djoko Tjandra cenderung lemah. Tapi, ingat! Walaupun sejak pelariannya pada 2009 silam hingga sekarang dia masih menyandang status buronan, kerajaan bisnisnya masih berdiri kokoh. Inilah yang membuatnya tampak memiliki bargaining di mata sejumlah kalangan, utamanya pebisnis. Djoko bisa saja memakai jaringannya untuk menekan otoritas terkait menjalankan keputusan tertentu yang bertentangan dengan hukum. Relasi politico-business ini relatif kurang tersentuh dalam debat publik dalam kaitannya dengan Djoko Tjandra.
Dari catatan MAKI (Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia), sekurang-kurangnya tercatat Djoko suda sering melakukan perjalanan keluar masuk tanah air. Jika catatan tersebut benar. Maka jelaslah suda kalau ada kekuatan politico-business, dimana ada jaringan dan aliansi oligarki predatorial, turut terlibat dalam memuluskan langkah dari sang buronan.
Ketiga oknum pejabat Polri yang terlibat dalam “persekongkolan” busuk ini bukanlah orang bodoh yang secara sukarela mempertaruhkan karier dan masa depannya membantu buronan yang secara politik tergolong lemah. Mereka paham betul apa konsekuensi bila persekongkolan ini terungkap. Jelas ada faktor lain yang jauh lebih esensial, tidak sekadar rendahnya integritas, yang membuat mereka berani mengambil risiko besar itu.
Antara Teknokratisme dan Revolusi
Djoko Tjandra adalah satu dari sekian banyak buronan yang masih ada dalam tahap pencarian. Preseden buruk yang hendak kita saksikan dan diperbincangkan ini sejatinya menegaskan bila negara tampak tidak berdaya ketika berhadapan dengan elite oligarki predator. Ini merupakan konsekuensi logis ketika politik kenegaraan dimenangkan faksi kapitalis, dimana implikasinya adalah negara menjelma menjadi negara kapitalis.
Lihat saja sejumlah peristiwa memilukan ketika negara dengan kejamnya terlibat dalam agenda penggusuran rumah rakyat miskin, termasuk lahan petani. Rakyat ditundukkan dengan senjata oleh aparatur represif. Namun bandingkan perlakukan negara kepada elite oligarki dimana ada insentif yang mereka dapatkan, sebagaimana beberapa bulan lalu presiden Jokowi memberikan subsidi kepada sejumlah konglomerat sawit. Bukankah semua itu sangat mencerminkan omong kosong keadilan sosial!?
Untuk menyudahi kemelut semacam ini agar terselesaikan dan tidak terluang, setidaknya ada dua opsi, namun sangat dilematis, untuk dipakai, yakni teknokratisme dan revolusi.
Kalau yang dipilih adalah opsi teknokratik. Maka persoalan yang diatasi tidaklah menyasar langsung pada akarnya, melainkan pada persoalan implikasi semata. Metode ini memang kerap digunakan dan nyatanya mampu mengatasi masalah hanya dalam rentang waktu, tingkatan dan derajat tertentu. Namun untuk memastikan masalah tersebut benar-benar hilang, tampak di titik itulah tidak ada jaminan.
Begitu pula dengan jalan revolusioner, membutuhkan perjuangan ekstra. Kondisi masyarakat dewasa ini yang cenderung terfragmentasi – baik di kalangan kelas buruh dan sebagainya – tampaknya sulit untuk menciptakan revolusi. Revolusi memang bukan hal yang mustahil, tetapi kalau berpijak pada kondisi objek sekarang, jelas untuk mendorong menetasnya revolusi butuh waktu yang tidak singkat.
Artikel Lainnya
-
72513/04/2025
-
109104/03/2025
-
85526/09/2023
-
Barbie (2023): Kritik Patriarki dan Inspirasi Feminisme untuk Indonesia
43730/11/2024 -
Makna Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia
55212/07/2024 -
Pentingnya Pendidikan Multikultural di Indonesia
211928/06/2023
