Mendeteksi Problem Komunikasi Pemerintah Memerangi Covid-19
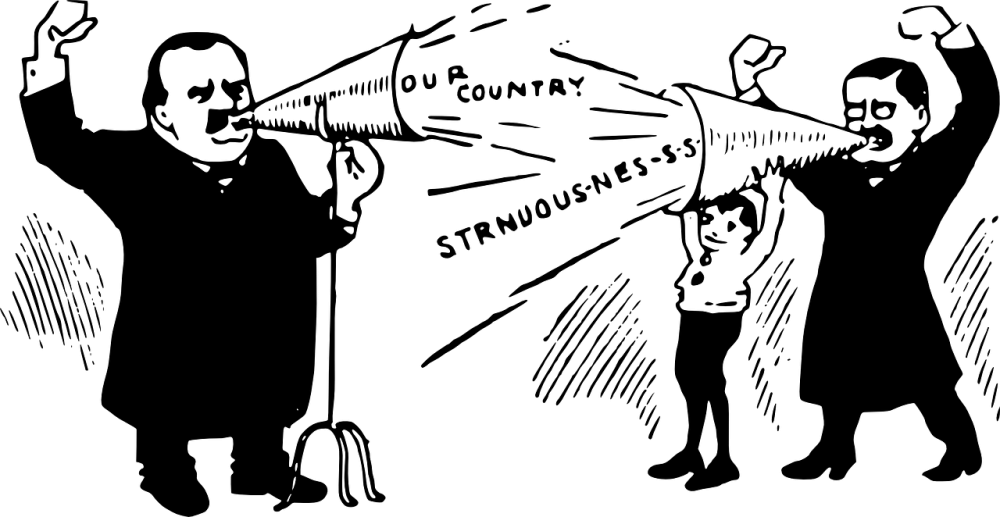
Dunia hari-hari ini sungguh berada dalam situasi kegamangan menghadapi pandemik Covid-19. Sebab, ketidakpastian menghantui: entah sampai kapan pandemik ini bisa berakhir. Mayoritas negara-negara menerapkan lockdown dan social distancing agar meminimalisasi penyebaran virus yang awalanya dideteksi pada desember 2019 dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ini.
Apapun nama strategi itu, pemerintahan tiap-tiap negara tidak bisa tidak, dalam menghimbaukan kebijakannya, menggunakan sarana komunikasi politik. Idealnya, sarana ini dipraktikkan oleh komunikator (pemerintah) secara efektif dan cerdas agar tidak ada distorsi pemahaman di antara komunikan/pendengar (masyarakat). Namun, bila yang terjadi sebaliknya, yakni kesimpangsiuran komunikasi dari pemerintah, tentu menciptakan problem. Kesimpangsiuran komunikasi politik terjadi manakala ketidakefektifnya komunikator dalam “mempertimbangkan apakah suatu hal atau ide harus dikomunikasikan atau tidak dalam satu sisi tertentu” (Pureklolon, 2016: 175). Inilah yang terjadi di Indonesia hari-hari ini.
Kesimpangsiuran itu bisa dilihat dari bagaimana komunikasi politik yang dipraktikkan pemerintah pusat, khususnya eksekutif, dalam dua pekan kemarin. Misalnya, pemerintah via Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly, mengusulkan pembebasan narapidana korupsi dengan kriteria tertentu, yakni “berusia 60 tahun dan telah menjalani dua per tiga dari masa hukuman pidana” (Rmolbanten.com, 4/4/2020), tetapi lantas diralat oleh staf Kantor Staf Presiden (KSP).
Bukan hanya itu, revisi pernyataan juga dilakukan oleh Mensesneg, Pratikno, terhadap Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman, “yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo membolehkan masyarakat mudik lebaran” (Kompas.com, 2/4/2020).
Menurut Pratikno, "Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," (sebagaimana dikutip Kompas.com, 2/4/2020). Inilah ilustrasi bagaimana komunikasi politik pemerinthan diprakktikkan di tengah sikon Covid-19 belakangan ini.
Mencermati kesengkarutan komunikasi pemerintah di atas, publik bisa menilai, pola komunikasi politik pemerintahan masihlah perlu diefektifkan. Pola komunikasi pemerintah hari-hari ini tentu membingungkan masyarakat.
Sudah cemas, bingung pula! Betapa tidak, masyarakat yang, misalnya seorang perantau merindukan kampung halaman, mendengar Jubir Presiden mengumumkan dibolehkannya aktivitas mudik lebaran, lantas ia bergegas kemudian terbang via pesawat, kesal sewaktu tiba di tempat transit ketika dikeluarkan bantahan pernyataan Mensesneg bahwa terjadi miskomunikasi.
Kesemrawutan komunikasi tersebut setidaknya disebabkan oleh tiga problem. Pertama, ketidakpaduan pandangan di internal pemerintah, khususnya eksekutif, dalam mengemas pesan komunikasi ke publik. Ketidakpaduan ide berakibat pada belum terbangunnya keseragaman pesan komunikasi politik dari pemerintah ke masyarakat. Ini terlihat ketika Jubir Presiden menyampaikan pernyataan yang malah bertolak belakang dengan maksud Presiden, bahwa masyarakat tidak perlu mudik. Tak ayal, miskomunikasi menyebabkan masyarakat gelagapan yang, mirisnya, justru datang dari pihak pemerintah sendiri.
Kedua, inefektivitas komunikator (ketidakefektifan pemberi pesan). Hemat saya, ini merupakan dampak dari problem pertama di atas (ketidakpaduan pandangan). Ketidakefektifan penyampai pesan ini karena tidak mempertimbangkan apakah substansi pesan telah dikelola (disetujui bersama) atau belum, untuk kemudian dinyatakan secara resmi ke publik. Jadi, pesan yang dikomunikatori oleh Jubir Presiden, dapatlah dikatakan sebagai, meminjam frasa dari Thomas Tokan Pureklolon (2016), “komunikasi politik yang tidak efektif”. Sebab, secara rasional, beliau belum berkonsultasi dengan Presiden, karena pernyataannya kemudian direvisi oleh Mensesneg. Inilah satu problem yang ke depan mesti diubah.
Ketiga, krisis kewibawaan Presiden sebagai kepala negara, yang mengarah pada klaim sepihak para pembantunya (Menteri). Kewibawaan, minimal dibutuhkan (ada) dari seorang kepala negara yang—apalagi dalam konteks pandemi ini—akan memerintah menterinya untuk mengkomunikasikan kebijakan: apakah masyarakat dibolehkan mudik lebaran atau tidak; masing-masing Rumah Sakit di daerah telah tercukupikah APD (alat pelindung diri)-nya agar pemerintah menyalurkan pada tanggal sekian (ini tugas Menteri Kesehatan!), misalnya. Nah, setelah disetujui, bolehlah disalurkan secara resmi ke publik. Karena Menteri adalah pembantu Presiden, maka pernyataannya--sebelum dikomunikasikan ke masyarakat--mesti dikonsultasikan ke presiden terlebih dahulu, atau minimal ke pihak KSP). Bukan sebaliknya, sebagaimana yang justru terlihat belakangan ini: KSP meralat pernyataan Menteri.
Tanpa deteksi ketiga problem di atas, maka rumit untuk menemukan solusi komunikasi politik pemerintah yang efektif dan cerdas, baik untuk saat ini maupun ke depan.
Artikel Lainnya
-
70216/05/2022
-
188904/04/2022
-
182609/02/2020
-
Mendukung Perawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya Selama Wabah Covid-19
203724/03/2020 -
Mafia Hukum dan Paradoks Keadilan Sosial di Indonesia
76027/04/2025 -
187705/04/2020
