Corona dan Elit Prokorupsi
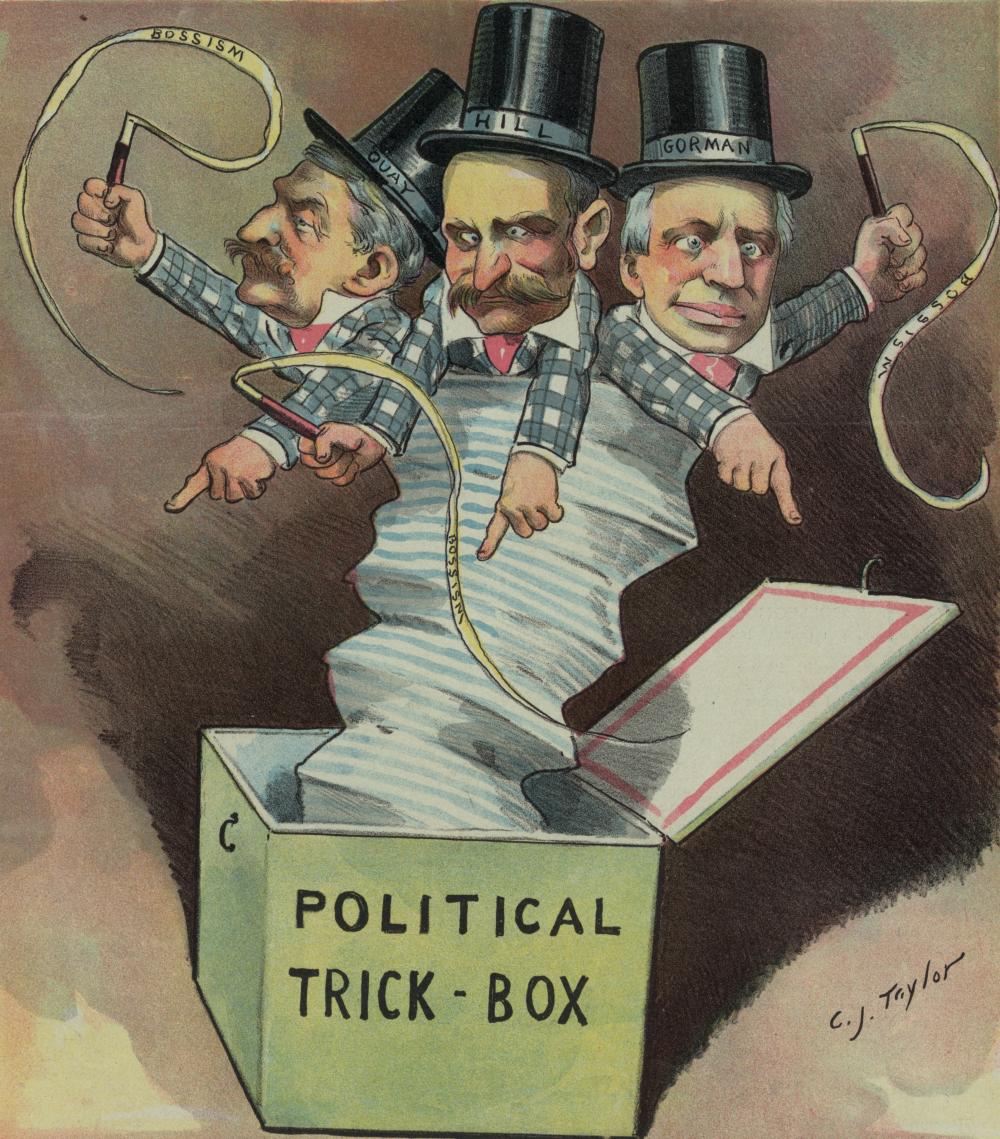
Menteri Hukum dan Hal Azasi Manusia Yasonna Laoly mewacanakan pembebasan terhadap puluhan ribu narapidana. Termasuk napi korupsi yang berusia 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa hukuman.
Hal tersebut ditempuh untuk mencegah penyebaran virus korona di rutan dan lapas. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Untuk napi kriminal yang menghuni sel berhimpit-himpitan bak ikan pindang, alasan tersebut mungkin bisa diterima. Apalagi sejauh ini kondisi lapas di Indonesia menurut Kemenkumham sudah over kapasitas hingga 700 persen. Kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia 130 ribu orang yang tidak sebanding dengan penghuni rilnya yang berjumlah hampir 270 ribu napi. Ini mengakibatkan kondisi lapas tidak sangat manusiawi.
Namun akan jadi ironi dan tidak masuk di nalar, jika pembebasan tersebut diberlakukan untuk napi korupsi. Mengingat kondisi lapas untuk para koruptor sesungguhnya berbeda dengan napi lainnya.
Napi koruptor sejauh yang kita tahu menghuni sel khusus. Satu napi menempati satu kamar. Seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin, di mana sel-sel dilengkapi dengan fasilitas mewah (menggunakan marmer, springbed, TV layar datar, pendingin ruangan, kulkas, kamar mandi seperti di kediaman pribadi yang dilengkapi water heater, dll).
Di Lapas Sukamiskin, para napi koruptor itu bisa membayar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta untuk mendapatkan fasilitas mewah seperti temuan mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Kompas 22/7/2018). Keistimewaan yang dimiliki oleh para koruptor di hotel prodeo tersebut sudah menjadi rahasia umum yang tidak digubris secara serius oleh pemerintah, sehingga penegakan hukum kita sulit menembus jantung keadilan publik.
Itu sebabnya wacana membebaskan napi koruptor hanya karena alasan darurat pagebluk korona, benar-benar tidak humanis dan mencoreng akal sehat. Nampak sekali tidak ada sensitifitas moral dari pejabat publik terutama terhadap perasaan rakyat yang selama ini telah begitu banyak menderita akibat hak-hak kesejahteraan mereka yang dirampas oleh koruptor. Yang terjadi sebaliknya, negara seolah membangun impunitas tebal terhadap napi korup dengan berbagai pengampunan dan pemberian remisi termasuk membuka pintu lebar-lebar bagi mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilu setelah bebas dari bui.
Kejahatan korupsi yang semestinya merupakan kejahatan extra ordinary yang memutilasi nilai kemanusiaan justru direduksi sebagai kapital untuk mengekalkan kekuasaan transaksional sebagaimana yang terejawantah dalam perilaku politik di organisasi politik kekuasaan dewasa ini.
Padahal jika mau jujur, perilaku korupsi yang dilakukan oleh para elite, selain berdampak memiskinkan rakyat, juga membuat imajinasi rakyat terhadap elite dan negara semakin buruk. Terutama terkait dengan kemampuan negara memberikan jaminan kepastian masa depan bagi rakyat di dalam bernegara (Ackerman, When is Corruption Harmful, 1999).
Negara dalam kondisi tertentu justru menjadi tempat konsolidasi para elite parpol pemburu rente untuk mengekstraksi kekayaan negara untuk dinikmati oleh sekelompok elite. Merujuk pada laporan Credit Suisse Research Institute misalnya, dikatakan bahwa kekayaan bangsa Indonesia mengalami peningkatan drastis mulai dari Januari 2010 hingga Juni 2011.
Dalam kurun waktu 1,5 tahun kenaikan kekayaan orang Indonesia mencapai US$ 420 miliar atau sekitar Rp 3.738 triliun. Ini membuat total kekayaan orang Indonesia pada pertengahan 2011 mencapai US$ 1,8 triliun atau sekita Rp 16.000 triliun.
Angka prominen tersebut membuat Indonesia menempati posisi ke-3 di kawasan Asia dan posisi ke-14 di dunia sebagai negara kontributor tertinggi bagi pertumbuhan kekayaan global.
Namun ironisnya, gemerlapnya prestasi tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi rakyat yang ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat ketimpangan kemiskinan antar-Jawa dan luar Jawa, termasuk makin menganganya jurang pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin.
Kondisi ini yang membuat subtilitas berdemokrasi kita sangat lemah di mata mondial. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada 1-7 Agustus 2018 mengkonstatasi bahwa meskipun 83 persen orang puas dengan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang baik, namun hal tersebut tidak ekuivalen dengan tingkat korupsi.
Artinya demokrasi yang dibangun selama ini tak lebih sebagai demokrasi ostentasial. Sekadar ritual elektoral dalam etalase pesta politik yang gagal mendeterminasi munculnya transofrmasi dalam aspek integritas, kualitas dan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan keseharian.
Hal tersebut diperparah pula oleh kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-berlakunya UU KPK baru, yang kelihatannya kian tersubordinasi oleh superioritas kekuatan politik yang membuat independensinya KPK kian tenggelam oleh hiruk pikuk kontestasi kepentingan di pucuk elite yang berbasis perburuan rente semata.
Survei Cyrus Network (24-30 Januari 2020) menunjukkan bagaimana kepercayaan publik terhadap KPK yang makin turun. 71 persen responden justru menilai Polri makin kuat, sedangkan KPK hanya dipersepsi kuat oleh 57 persen.
Hasil survei itu sebenarnya tak perlu membuat kita kaget. Karena menurut Boni Hargens itulah tujuan dari cara kerja oligarki yang mewabah di tubuh parpol kita (Kartelisasi Oigarkis, Kompas 28/3/2020).
Para (elite) politisi parpol berusaha membangun keutuhan pengaruh (politik dan ekonomi) secara lintas ideologi untuk mengakumulasi kekayaan material. Fraksi-fraksi yang ada di parlemen termasuk aktor-aktor yang memerintah di lingkaran eksekutif, saya kira mempraktekkan syahwat itu selama ini. Sehingga bukan kepentingan rakyat lagi yang disuarakan dan diperjuangkan, tetapi kepentingan para elite yang kebetulan merupakan pemodal sentrum di parpol.
Apa yang diwacanakan oleh Menkumham di atas telah turut mendistorsi upaya keras negara dan rakyat dalam mengeliminasi penyakit korupsi. Pernyataan pejabat yang sangat jauh dari nilai keutamaan empati dan bela rasa (compassion) karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Padahal menurut Aristoteles dalam bukunya Politics, sikap empati adalah fondasi berpikir seorang politisi dalam mempertimbangkan suatu keputusan agar eksistensinya mampu memberi kontribusi etis-moral bagi publik. Tanpa itu, makna politisi akan kehilangan esensinya.
Selain itu pula, dalam diri seorang pejabat mestinya terkandung introduksi moral dan tanggung jawab etis untuk mendahulukan kepentingan bangsa dalam konteks bersama-sama memberantas apa yang menjadi akar penyebab kemiskinan dan ketertinggalan politik-ekonomi bangsa ini. Karena tanpa nilai tersebut, sesungguhnya mereka akan kehilangan representasi serta legitimasi etis-politiknya di hadapan publik (William, 2003:38-39).
Padahal, hanya itu yang bisa menghindarkan diri mereka dari involusi (penciutan makna) statusnya sebagai seorang pejabat yang subtil mendedikasikan panggilannya untuk terwujudnya bonum commune (kemaslahatan bersama).
Yang kita khawatir, upaya membebaskan napi koruptor yang digaungkan oleh pejabat publik sekelas Menkumham tersebut akan menjadi justifikasi banalitas bagi para koruptor dari pusat sampai daerah untuk terus mencari celah untuk merampok uang negara di tengah propaganda perang terhadap korupsi yang terus dihembuskan oleh Presiden maupun KPK. Akhirnya bukan demokrasi yang diraih kelak, sebaliknya “demokorupsi”. Yaitu masifnya korupsi oleh para politisi dari hari ke hari melalui pelbagai strategi, modus, yang kemudian diglorifikasi di panggung-panggung utama kekuasaan dari pusat sampai lokal.
Tentu saja bukan mimpi buruk itu yang kita harapkan. Demokrasi tidak boleh tersandera oleh sistem politik oligarki yang destruktif dan kanibalis tersebut. Seluruh elemen bangsa, termasuk rakyat yang digerakkan oleh akal sehat harus berani dan mampu menumbangkan “demokorupsi” yang memiskinkan rakyat dan menciderai substansi demokrasi tersebut. Termasuk melawan segala rasionalitas yang coba dibangun oleh para elite yang ujung-ujungnya ingin melemahkan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Kita berharap Presiden, sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, terus merawat semangat perlawanan terhadap rasuah. Terutama dengan menegur secara tegas para menterinya yang berperilaku tidak sejalan dengan agenda pemerintah, atau yang secara “subliminal” ingin berkompromi dengan para koruptor.
Artikel Lainnya
-
144406/12/2021
-
209602/10/2020
-
200727/09/2019
-
Suasana Natal di Dusun yang kecil
95911/12/2023 -
Meminimalkan Problematika Pembelajaran Jarak Jauh
81622/07/2021 -
Etika Komunikasi di Media Sosial
182419/09/2021
