Antara Hukum dan Kodrati Manusia
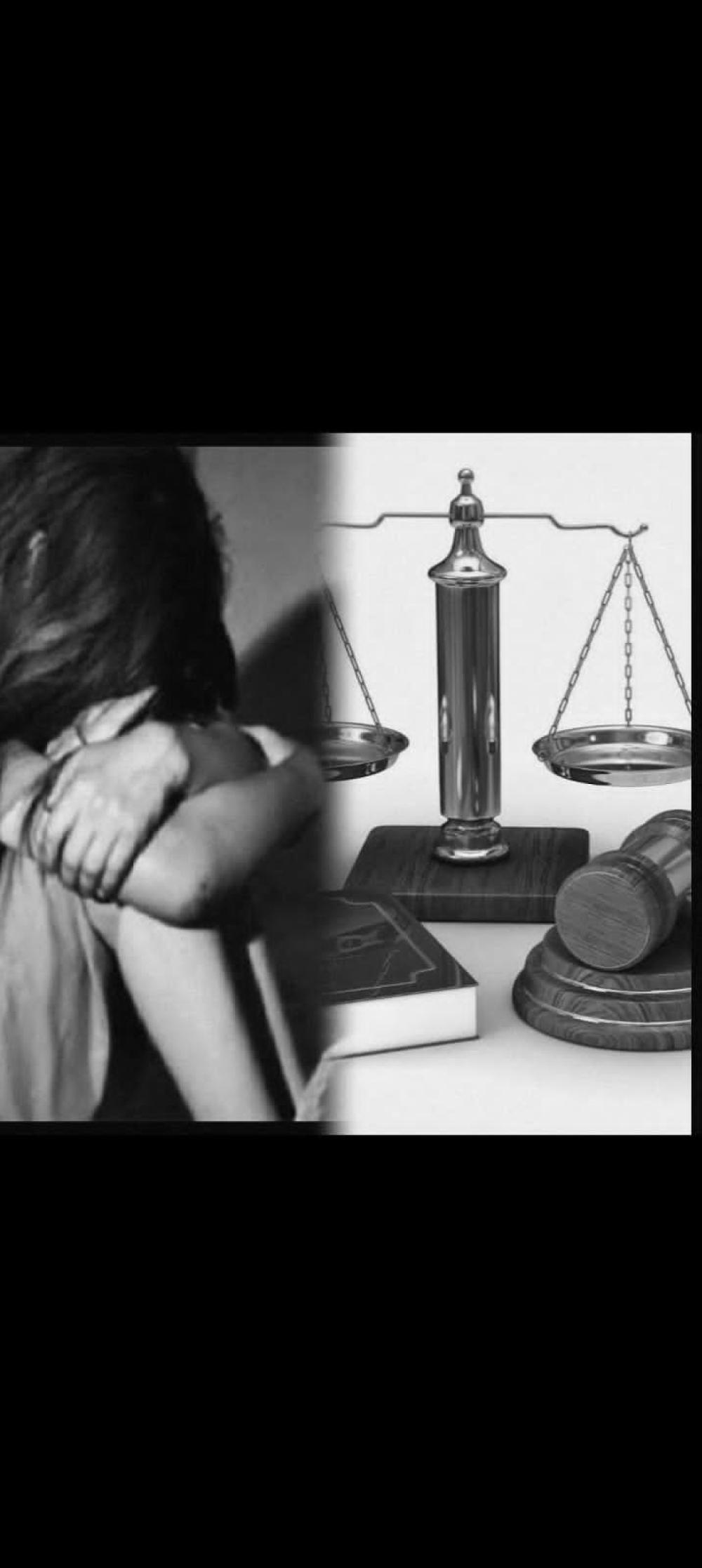
Hukum selama ini sering diposisikan sebagai pelindung utama masyarakat—perisai ketika hak-hak dasar terancam dan benteng terakhir dalam menegakkan keadilan. Namun, dalam praktik sehari-hari, hukum sering kali kehilangan fungsi kodratinya. Ia justru tampak kaku, terjebak pada formalitas prosedural, dan menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar kelahirannya. Nurrohman (2019) menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai teks normatif yang kering; ia seharusnya hadir untuk menjunjung martabat manusia dan merespons kebutuhan hidup bermasyarakat. Tetapi, realitas di lapangan menunjukkan hukum yang dingin dan minim empati.
Manusia, secara kodrati, menginginkan hal-hal mendasar: dihargai, dilindungi, dan diperlakukan dengan adil. Pertanyaannya, mengapa hukum yang lahir dari kebutuhan manusia justru kerap gagal menjamin hak-hak itu? Mengapa dalam banyak kasus hukum lebih tunduk pada kepentingan politik, kekuasaan, bahkan uang? Hadjon (2005) menyebut kondisi ini sebagai terbentuknya jurang yang lebar antara “das sollen” (hukum yang seharusnya) dan “das sein” (hukum yang nyata di lapangan). Apabila hukum hanya menjadi alat kepentingan tertentu, bukankah ia telah kehilangan ruhnya sebagai sarana keadilan?
Contoh nyata yang menggambarkan rapuhnya penegakan hukum dapat kita lihat pada kasus tragis di Kolaka Timur. Seorang anak yang hendak berangkat mengaji dibunuh dengan kejam di jalan umum. Tragedi ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan perampasan hak paling fundamental yang dimiliki setiap manusia sejak lahir: hak hidup. Pasal 28A UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jika hak kodrati ini dilanggar, lalu di mana posisi negara yang seharusnya hadir untuk menjamin perlindungan tersebut?
Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan cara demikian seharusnya dijerat dengan pasal berat. Pasal 340 KUHP mengatur bahwa pembunuhan berencana dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup. Namun dalam praktik, sering kali pelaku hanya dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Jika demikian, bukankah hal ini menciderai rasa keadilan publik? Apakah benar nyawa seorang anak hanya sepadan dengan tujuh tahun penjara?
Satjipto Rahardjo (2009) pernah mengingatkan bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan, melainkan harus “dihidupkan” dengan nilai moral dan nurani. Bila hukum hanya dipahami sebagai prosedur teknis, ia akan kehilangan misinya sebagai pelindung martabat manusia. Pertanyaan yang mengusik hati kemudian muncul: Apakah hukum kita masih memiliki sisi kemanusiaan, atau hanya menjadi mesin administrasi yang kaku?
Kasus Kolaka Timur bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga menjadi ujian serius bagi kredibilitas hukum Indonesia. Nyawa seorang anak bukan sekadar kehilangan bagi keluarganya, tetapi juga luka bagi nurani bangsa. Jika hukum tidak mampu memberi keadilan yang setimpal, bukankah kepercayaan publik terhadap institusi negara akan semakin terkikis? Komnas HAM (2023) mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin hak hidup warganya. Namun, jika putusan pengadilan justru ringan, siapa yang akan memulihkan luka masyarakat dan menjawab keresahan publik?
Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah mungkin nilai sebuah nyawa dapat ditebus hanya dengan vonis singkat? Apakah negara benar-benar hadir sebagai pelindung rakyat, atau justru menjadi saksi bisu dari ketidakadilan? Dan jika hukum tidak lagi mampu menegakkan keadilan bagi korban paling rentan, lalu apa arti keberadaannya?
Pada akhirnya, antara hukum dan kodrat manusia tidak dapat dipisahkan. Hukum lahir dari kebutuhan manusia untuk hidup bermartabat, adil, dan aman. Hak hidup sebagai hak kodrati tidak boleh dipermainkan dengan dalih prosedur hukum yang sempit. United Nations Human Rights (2022) menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Dengan demikian, penegakan hukum seharusnya tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berpijak pada nurani.
Sebagaimana dikatakan oleh Yuril Isha Mahendra, “Hukum harus menjadi alat pemersatu rakyat, bukan pemecah belah kehidupan sosial.” Oleh karena itu, sudah saatnya hukum Indonesia dikembalikan pada orientasi kodratinya: untuk melindungi, bukan melukai; untuk mengayomi, bukan mengabaikan. Pertanyaan terakhir yang patut direnungkan adalah: apakah kita akan terus membiarkan hukum berjalan tanpa nurani, ataukah kita berani mendorong perubahan agar hukum benar-benar kembali berpihak pada manusia?
Artikel Lainnya
-
9911/07/2025
-
30103/01/2025
-
13628/06/2025
-
Benarkah Balai Pustaka adalah Pelopor Sastra Modern di Indonesia?
17223/08/2025 -
Raja Ampat dan Himpitan Berbagai Elemen Kepentingan
42317/06/2025 -
Aksi Kamisan dan Upaya untuk Memperjuangkan HAM di Indonesia
42519/07/2024
