Seni dan Batasan-Batasan
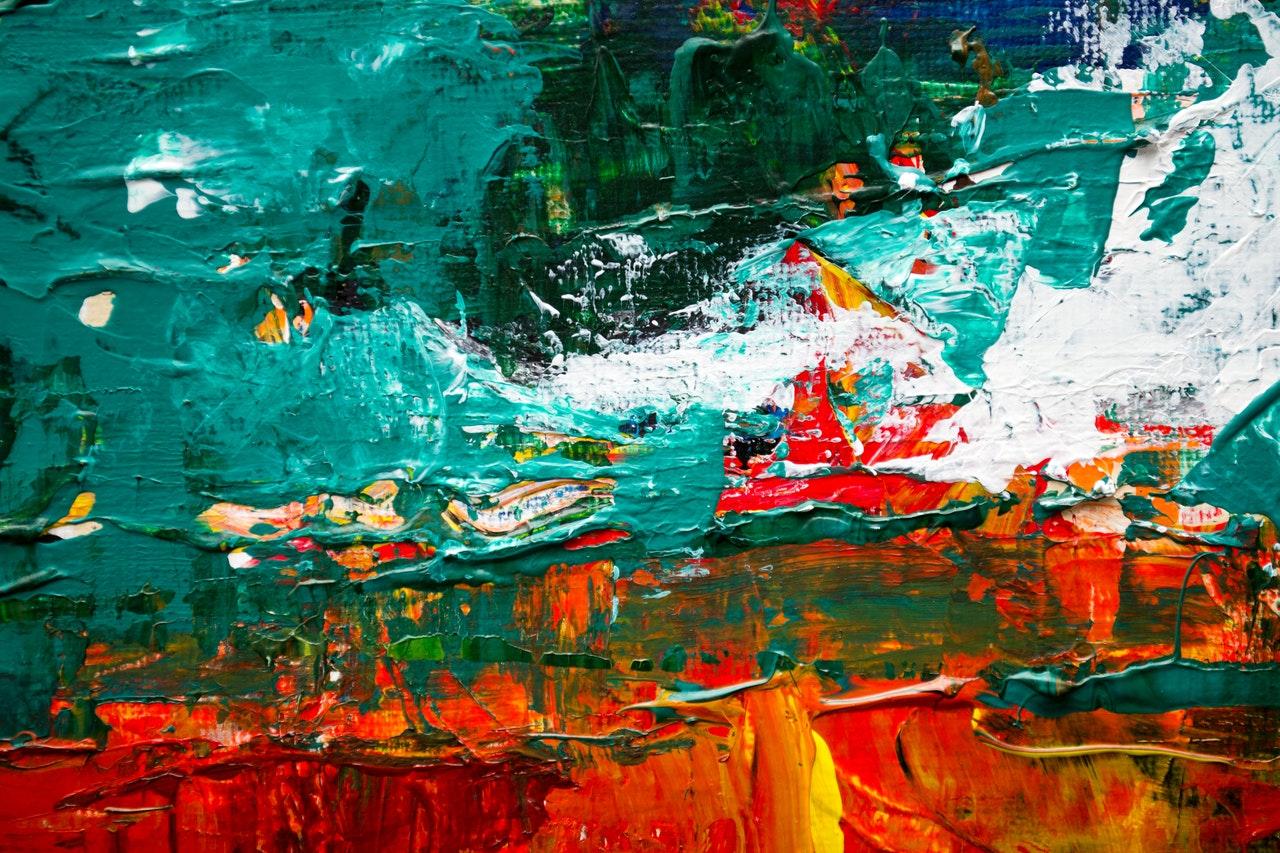
Seni telah menjadi bagian besar dalam sejarah manusia. Perkembangan peradaban dan masyarakat tak lepas dari penghargaan dan perubahan bentuk-bentuk seni. Seni berkembang, berdenyut sepanjang zaman, dinamis, menginspirasi dan mendorong taraf kehidupan miliaran manusia di dunia menjadi lebih berarti.
Di kala manusia awal penat pada pola kehidupannya yang keras dan tak kenal ampun, musik diciptakan untuk menghibur. Tarian ditampilkan untuk melepas rantai-rantai psikologis yang membebani manusia pada saat wabah dan kematian menyeruak berjamaah. Dengan daya pikir yang masih rawan, manusia menyulap sebongkah batu atau kayu menjadi ukiran simbolis bernilai estetis serentak religius. Lukisan-lukisan tangan di dinding-dinding gua menyampaikan pesan alam semesta dan imajinasi terdalam manusia. Semuanya adalah seni.
Barangkali seni adalah hal-hal yang lazim kita jumpai. Barangkali yang dimaksud sebagai seni adalah segala sesuatu yang kita lihat sambil lalu, yang kita gunakan secara mekanis tanpa perlu dipikirkan atau yang selalu kita kenakan. Seni bisa jadi adalah benda yang di mata kita tidak bernilai seni. Lantas apa batas-batas dari seni? Bagaimana sebuah karya dan hasil kerja manusia bisa disebut sebagai sesuatu yang bernilai seni?
Pada tahun sekitar 1961, kotoran manusia adalah seni. Piero Manzoni, seniman Italia, mengemas 90 kaleng berukuran 4,8 x 6,5 cm berisi 30 gram kotorannya sendiri. Seakan masih kurang menarik, pada bagian luar kaleng tertera label dalam bahasa Inggris, Jerman, Italia dan Prancis sekaligus berbunyi: “Kotoran Seniman. Isi 30 gram. Diawetkan dengan baik. Diproduksi dan dikemas pada bulan Mei 1961.” Kumpulan kaleng berwarna coklat tua itu diberi nama Artist’s Shit. Dalam proses pelelangan di tahun 2007, harga satu kaleng tersebut mencapai sekitar 124.000 euro (sekitar 2 miliar). Kotoran Manzoni dalam kaleng tersebut dianggap sebagai seni bernilai estetis sehingga orang berani merogoh koceknya hingga miliaran rupiah.[1]
Hitung-hitungan tentang harga, lukisan karya Gerhard Richter tak kalah membingungkannya. Pelukis asal Jerman ini menciptakan sebuah lukisan yang ia beri judul ‘Red Mirror’ (Cermin Merah). Tepat seperti namanya, lukisan itu berupa sebidang kanvas yang diberi warna merah seluruhnya. Tidak ada objek yang digambarkan di sana. Sejauh mata memandang, lukisan itu hanya membiarkan mata kita menyaksikan lapisan warna merah tanpa embel-embel apa pun. Tampaknya pelukis menggambarkannya sebagai sebuah cermin yang berwarna merah. Lukisan itu dilihat sebagai sebuah seni. Hal ini terlihat dari nominal hasil penjualannya yang mencapai $750.000 (sekitar Rp. 1,8 miliar).[2]
Karya sejenis juga sempat dipamerkan di galeri Museum of Non-Visible Art, New York. Berbeda dari Red Mirror yang ditampilkan dengan warna tunggal merah, di galeri tersebut terpampang banyak bingkai lukisan tanpa warna apa-apa. Hanya ada bingkai kaca dan lembaran putih polos di dalamnya. Tak mengherankan lukisan-lukisan tersebut diberi nama “Non-Existent Art” (karya seni tak terlihat).
Pengunjung yang datang hanya bisa menebak dan membayangkan lukisan apa yang tertera di dalamnya. Karena lukisan ini dianggap bernilai seni, seorang wanita membanderolnya dengan harga $ 10.000 (sekitar Rp. 144 juta). Lukisan yang ia beli berjudul Fresh Air, tak ada gambar, tak ada objek. Karya seperti ini juga dilihat sebagai sebuah seni.[3]
Seni: Seorang Anak Nakal?
Definisi tentang seni bernilai subjektif. Apa yang dianggap mengandung nilai seni di benak seseorang bisa jadi hanya sekedar sampah di mata orang lain. Apa yang tampak kotor dan menjijikkan ternyata dilihat punya daya tarik estetis mahal. Dalam posisi ini, siapa pun rentan untuk ditipu dan menjadi orang dungu. Para seniman bisa saja membesar-besarkan hal remeh temeh sebagai seni. Sejalan dengan itu, para penikmat bisa jadi terlalu terobsesi mengklaim ‘semua’ karya seniman sebagai bernilai seni tinggi—semakin tinggi harga yang dipatok, semakin tinggi pula nilai seninya.
Untuk menghindari pra-anggapan bahwa segala sesuatu adalah seni, diperlukan sebuah standar. Standar ini berlaku untuk semua hal. Layaknya sebuah pagar, titik tolak ini memisahkan dan memilah yang bernilai seni dan yang tidak. Pada dasarnya ada tiga nilai utama yang mengklasifikasikan sesuatu sebagai seni. Tiga nilai tersebut harus terkandung dalam seni: nilai keindahan, nilai pengetahuan dan nilai kehidupan.[4]
Nilai keindahan berkaitan dengan apa yang dicerap oleh indra manusia. Keindahan visual ditangkap oleh mata. Keindahan audio dicerap oleh telinga. Keindahan bentuk, rasa dan tekstur dipahami oleh indra perasa. Segala sesuatu yang bernilai indah memuaskan indra-indra.
Selain itu, ada keindahan yang tak kasat mata yang hanya bisa dicerap oleh intuisi dan rasa batin. Keindahan semacam ini berada pada tataran yang lebih luhur dan tinggi. Dalam hal karya seni lukisan misalnya, keindahan yang kasat mata tampak dalam bentuk gambar dan panorama lukisannya sedangkan yang tak kasat mata hanya dapat dijumpai melalui penggalian refleksi dan inspirasi dari karya seni bersangkutan. Makna simbolik sebuah karya juga termasuk di dalamnya.
Nilai pengetahuan terkandung dalam karya seni. Seni tidak sekedar tentang olah rasa melainkan pula olah pikiran. Pengetahuan diperlukan untuk membuat suatu karya seni. Pengetahuan membentang dari teknik pembuatan, medium yang digunakan, gaya kreasi seniman dan tema yang melatarbelakangi karya bersangkutan. Seluruh paket pengetahuan ini memisahkan seni dari karya yang dibuat asal-asalan.
Seni semakin menjadi bernilai bila ia mencakup sumbangan untuk kehidupan personal maupun sosial. Seni rupa patung Soekarno di rumah pengasingan di Ende bukan sebuah totem untuk dilihat sekilas atau bahkan disembah. Ia harus mengkawal para penikmat kepada untaian pelajaran hidup: patriotisme, nasionalisme, keterbukaan, pengorbanan, kebesaran hati, perjuangan. Butir-butir kualitas ini bisa digali dari sebongkah patung yang nantinya, bila dihayati dan dilaksanakan, akan menjadi sebuah norma yang meningkatkan kualitas hidup pribadi dan bersama.
Ketiga standar ini bukanlah patokan kebenaran final untuk menilai seni. Seni jauh lebih fleksibel dan adaptif menyerap perubahan bagai spons. Kreativitas manusia selalu berkembang, demikian pula seni. Ekspresi dan perasaan manusia selalu beragam, demikian pula seni. Akhirnya, pagar (dibaca standar) yang telah kita buat bukanlah pembatas ketat yang mampu memilah ketidaksenian dari kesenian. Di ‘pagar’ tersebut masih tersisa celah-celah dan rongga halus di mana definisi tentang seni masih melanggar batasan-batasan umum atau konvensional.
Seni bagaikan seorang anak nakal yang melanggar aturan. Ia memasuki teritori-teritori baru penuh tantangan. Berani bermain di wilayah kotor dan menjijikkan tapi menjanjikan kesenangan dan kebebasan. Ia dilahirkan untuk menipu semua aturan dan batasan. Dari sini ia mendapatkan kreativitasnya (atau kebodohannya?). Dengan demikian, di satu sisi, seni sebenarnya adalah kekuatan yang menentang segala kemapanan.
Pertanyaan tentang arti ultim dari seni merupakan pencarian terbuka. Sebagaimana sifat seni adalah ‘menentang batasan’, demikian pula definisinya adalah penggalian tak berhingga dari batasan-batasan seni. Setiap detik, karya seni membuka pintu-pintu kemungkinan baru. Sejauh ia merupakan ungkapan jujur dari kreativitas dan aspirasi manusia, hal itu bisa dianggap sebagai seni.
Dengan demikian, ada dua batasan seni: subjektivitas dan objektivitas. Secara subjektif seni dikenal melalui perasaan dan pemahaman pribadi tertentu. Sejauh sesuatu dianggap menyentuh hati dan memuaskan rasa keindahan seseorang, baginya hal itu adalah seni. Sesuatu tidak bernilai seni bila ia tidak dirasa demikian oleh orang bersangkutan, meskipun bagi orang lain ia dilihat sebaga seni. Secara subjektif, segala sesuatu bisa bernilai seni.
Sebaliknya secara objektif, standar-standar baku diterapkan untuk membedakan objek mana yang seni dan objek mana yang tidak. Standar ini berlaku untuk segala hal agar orang yang tidak berjiwa seni bisa memahami dan mengapresasi suatu karya sebagai seni. Dengannya, orang tidak mudah dibodohi untuk menerima segala sesuatu sebagai seni. Secara objektif, tidak semua hal bernilai seni.
Referensi:
[1] Bayu Baharul, “7 Karya Seni Aneh yang Bisa-Bisanya Laku Terjual dengan Harga Mahal”, Selipan.Com, Selasa, 28 Juli 2020.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Muhammad Noor, Ensiklopedia Mengenal Dunia: Seni Rupa, Musik, Tari, Teater dan Seni Menulis (Jakarta: Trias Yoga Kreasindo, 2010), hlm. 3-4.
Artikel Lainnya
-
54825/08/2024
-
109814/03/2023
-
22506/12/2024
-
Krisis Jurnalisma Indonesia di Tengah Gelombang PHK Massal
27229/06/2025 -
Dana Desa: Penggerak Cakra Pembangunan
164630/05/2020 -
Komunikasi Pasca Corona: Dunia Maya (Bisa) Terasa Nyata
248602/05/2020
